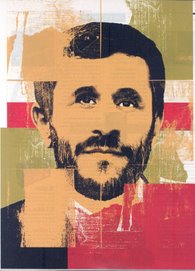BALADA WARTAWAN INDONESIA
(Di antara Ruang Berita dan Penjara)
Kami hanyalah sekumpulan Wartawan,
Yang bersenjatakan pena dan bukan senapan.
Kami mengandalkan otak dan kecerdasan,
Bukan otot dan kekerasan.
Di antara ruang berita dan penjara,
Di situlah kami berada,
Mengais, memulung dan menyebarkan berita,
Semata-mata bagi kepentingan publik belaka.
Kadangkala goresan pena kami terasa tajam menusuk mata
Bagi kalangan yang menghianati jabatannya,
Atau mereka yang takut perbuatannya menjadi kasat mata
Seperti para koruptor dan polisi yang bersekutu dengan mafia.
Wahai para koruptor, diktator dan manipulator,
Pokoknya semua yang melakukan pekerjaan kotor,
Kami menulis sepak terjang kalian bukan dengan rasa benci,
Tapi dengan rasa sedih, hati yang pedih: mengapa kalian menghianati bangsaini?
Bukankah sudah ratusan ribu pejuang negeri ini,
Tumpah darahnya demi kemerdekaan ibu pertiwi.
Demi merebut kemerdekaan, demi mewariskan masa depan yang lebih cemerlang,
Akankah pengorbanan itu kalian sia-siakan, hanya demi sejumlah uang?
Kami mungkin hanyalah sekumpulan wartawan,
Yang mengais, memulung dan menyebarkan berita kepada setiap orang,
Namun biar pun hujan gugatan, penjara dan peluru menghadang,
Kami tetap akan terus menulis dan berjuang, karena kami harus menjaga kemerdekaan.
Jakarta 17 Agustus 2004
BHM
I am a Journalist
Sembilan tahun yang lalu saya berdiri disini membacakan sesuatu yang namanya pembelaan, kerennya dalam bahasa Belanda disebut pleidooi. Tempatnya di ruangan ini, cuma bedanya dulu tak berAC, bukan berlantai keramik. Majelis Hakim dan jaksanya tentu juga beda. Pembelaan atas tuduhan jaksa penuntut umum atas nama 'negara' yang membacakan tuntutan hukuman pidana penjara terhadap saya (dan juga kolega saya yang sepantasnya saya sebut ayah atau paman, Teuku Iskandar Ali).
Kenapa 'negara' saya kasih tanda kutip? Menurut ahli Bahasa Indonesia, kata dalam "..." adalah bukan dalam arti sebenarnya, atau metamorphosis. Saya pikir Jaksa dan juga para penegak hukum lain sebelum lulus pendidikan sarjananya, sudah pasti juga lulus pelajaran bahasa Indonesia. Tentu tahu tanda-tanda baca itu, kan?
Dalam mengajukan dakwaan, selama proses peradilan dan pembacaan tuntutan Jaksa seolah-olah atas nama negara, mewakili warga negara yang 'dirugikan' yang kebetulan bernama Tomy Winata. Tapi melihat proses di kepolisian, dakwaan jaksa sampai tuntutan saya meragukan apa yang dilakukan jaksa benar-benar mewakili warga negara yang 'dirugikan'. Saya melihat yang dilakukan jaksa adalah untuk kepentingan 'diri' atau 'korps'-nya atau juga kepentingan orang yang bernama Tomy Winata itu. Dari cara-cara yang dilakukan selama proses persidangan sampai pembacaan tuntutan saya tak melihat jaksa sebagai sosok obyektif yang mewakili negara. Semiskin-miskinnya saya sebagai 'pemulung informasi', tiap bulan gaji dipotong untuk membayar pajak. Dari pajak itulah diantaranya untuk membayar bapak jaksa yang menuntut saya dihukum penjara dua tahun ini.
Jadi ingat Pak Jaksa, uang yang anda makan sampai pensiun nanti itu adalah uang hasil keringat rakyat yang dikumpulkan negara untuk anda. Anda sampai seumur hidup digaji oleh rakyat, bukan dibayar oleh seseorang yang hanya perkaranya ingin 'dimenangkan'. Karena orang tersebut hanya sesekali selama mempunyai perkara. Saya gak tahu kalau ada jaksa yang dibayar seumur hidup atau dana yang diterimanya melebihi biaya hidupnya sepanjang hajat oleh seseorang?
Saya sungguh sedih dan prihatin melihat Jaksa yang baik, Almarhum Jaksa Silalahi harus meninggal ditembak seseorang di Palu. Sementara jaksa-jaksa busuk hidup berkeliaran 'memperdagangkan' perkara. Saya tak rela jaksa-jaksa yang berguna bagi nusa bangsa dan ummat manusia, harus mati muda, sementara yang lainnya menodai korps-nya. Saya mau tanya jalan mana yang anda pilih hai jaksa penuntut umum? Jalan yang telah ditapaki Jaksa Silalahi, Baharudin Lopa, M.Yamin atau jalan para jaksa yang menodai korps dan keadilan? Silakan anda tanya hati nurani anda sendiri, dan biarkan masyarakat menilai cara kerja anda sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum.
Majelis Hakim Yang Dihormati,
Apakah Bapak-bapak majelis hakim kenal Tintin? Saya ketika masih di Sekolah Dasar, sudah mulai baca komik itu. Waktu itu (sekitar tahun 1975-77) saya pengunjung tetap perpustakaan Balai Pustaka di dekat Lapangan Banteng (Bulakan sapi lanang, kata orang Tegal), Jakarta Pusat. Kalau bapak belum pernah baca, tanya ke anak bapak, siapa tahu mereka juga pernah baca.
Komik Tintin menggambarkan betapa dunia wartawan adalah dunia khayal yang indah, menyenangkan, sekaligus penuh petualangan dan bahaya. Herge menggambarkan Tintin yang tidak pernah kuatir dengan uang di saku, juga tidak pernah diperlihatkan memeriksa buku rekening banknya. Tintin selalu ingin tahu, sekaligus cermat dan hati-hati. Ingatannya panjang tapi ia tidak segan mencatat hal-hal kecil seperti nama, alamat juga warna baju seseorang, dan ini amat membantunya dalam merangkai beberapa peristiwa menjadi sebuah untaian kesimpulan.
Tidak penakut, tapi tidak pernah menantang bahaya. Selalu kreatif dalam mencari jalan keluar ketika telah tersudut tapi juga selalu bernasib untung. Berteman dengan banyak kalangan, dari mulai seorang anak nun jauh di atas pegunungan Himalaya, sampai anak Raja dari Timur Tengah. Polisi dan Pengusaha. Penyanyi, ilmuwan juga pengusaha yang ternyata gembong mafia dan akhirnya berusaha membunuhnya.
Di beberapa episode, kisah-kisah petualangan Tintin, diakhiri dengan sekuel laporan yang dimuat sebuah koran di AS. Demikian karakter Tintin digambarkan. Jika dicermati, Herge (sang pengarang) rupanya berkeyakinan, wartawan seperti Tintin akan selalu menuai bahaya. Semua kisah petualangan Tintin selalu menghidangkan ketegangan yang mengancam jiwa, meski Herge selalu membuat nasib Tintin beruntung. Berbagai ancaman telah dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Nyaris ditembak mati di depan barisan tentara mabuk. Dimakan hiu. Didorong dari atap kereta api yang melaju. Dan masih banyak lagi. Sedikit banyak kemiripannya, begitulah dunia wartawan.
Pekerjaan ini tidak sama dengan pekerjaan seorang Sekretaris yang setiap hari duduk di kursi kantor, menunggu perintah dari majikannya sambil berhadapan dengan komputer dan telpon. Seseorang tidak mungkin menjadi wartawan, jika ia tidak pernah ingin tahu atas sesuatu dan punya keinginan kuat untuk mencari jawaban yang benar dari keingin-tahuannya itu. Mungkin, boleh dibilang, wartawan adalah seorang filosof. Dalam bahasa Latin, philo berarti suka atau beuki (ini dari bahasa Sunda), sementara sophie adalah pertanyaan. Jadi, filsuf adalah orang yang suka bertanya-tanya. Tapi di sinilah persoalan lain muncul, karena mencari jawaban ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan keingin-tahuan pun tidak perlu dimiliki oleh oknum yang ingin diaku sebagai wartawan, karena dia bisa saja bergerombol seperti ikan tuna, pergi ke sana pergi ke sini, wara wiri mencari narasumber lalu akhirnya mencari sedekah. Ini yang disebut wartawan gadungan.
Wartawan asli, seperti Tintin, memiliki rasa ingin tahu yang besar karena didorong oleh kepedulian terhadap kehidupan sosialnya. Pada nilai-nilai moral yang harus ditegakkan. Bukan pada kebutuhan perut sendiri. Dalam komik itu tidak pernah digambarkan upacara rutin makan pagi, siang dan malam, bukan? Itu menunjukkan pandangan Herge tentang wartawan, betapa kepentingan individualis sang wartawan menjadi amat tidak relevan dalam pekerjaan kewartawanan. Tintin tidak pernah vested interest, melainkan pada Public Interest.
Herge mungkin bukan seorang pakar Jurnalistik, tapi ia lebih dulu mengungkapkan melalui gambar-gambar komiknya, elemen-elemen dasar jurnalisme yang di kemudian hari dirumuskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai elemen dasar jurnalistik. Menurut Kovach dan Rosenstiel, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran dan bla-bla-bla seterusnya. Eleman dasar itu, mengundang konsekuensi seperti yang dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Ditembaki, dst. (oh, nasibku .. sopo sing tresna).
Wartawan menjalankan tugas untuk memenuhi hak azasi warga negara untuk (1) mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan dalam mengelola negara, (2) untuk berpendapat dan (3) memperoleh informasi.
Inilah sebabnya, mengapa gangguan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya, disejajarkan dengan gangguan terhadap hak rakyat dan demokrasi. Bahkan di daerah perang, wartawan hadir untuk menjamin hak rakyat untuk tahu. Tanpa kehadiran wartawan, rakyat AS tidak tahu kalau tentaranya melakukan apa saja di Vietnam, sehingga muncul gelombang besar menentang mobilisasi ke Vietnam.
Tanpa kehadiran wartawan, dunia internasional tidak pernah tahu jika tentara AS menggunakan bom kimia bernama NAPALM di Vietnam. Tanpa kerja pers, kita tidak tahu sejumlah caleg di Jawa Tengah ternyata memalsukan surat keterangan kesehatan dan di antara mereka ternyata dinyatakan sakit jiwa.
Tanpa kerja wartawan, kita juga tidak tahu jika sebuah partai di Lampung ternyata mencalonkan seorang perampok sebagai calon anggota legislatif. Kemudian hari si perampok tewas dihajar peluru polisi, sebelum KPU mengumumkan daftar calon tetap tanggal 29 Januari lalu.
Jadi memang wajar, jika banyak pihak begitu geram melihat kehadiran wartawan. Karena mereka tidak ingin "ketahuan belangnya". Orang beginian yang merasa harus "ngamplopin" wartawan supaya bisa tidur tenang. Atau orang yang tidak mau bertanggung jawab pada publik.
Sebagai profesional yang menyadari tugas sebagai pengemban hak publik, wartawan memiliki perangkat Kode Etik agar interaksi wartawan dengan lingkungan sekitarnya ketika bekerja dan hasil karyanya benar-benar memenuhi standard. Selain berhak membuat berita, wartawan juga wajib hukumnya patuh pada kode etik. Di sinilah mengapa Tintin mengenal banyak orang.
Pendapat dan selera pribadi, tidak penting dalam kehidupan wartawan. Ia harus mau mendatangi kompleks pelacuran dan mewawancarai pelacur untuk mengimbangi berita tentang kompleks pelacuran. Ia harus mau bersalaman dengan penderita HIV/AIDS. Juga tetap mewawancarai seorang Presiden yang keji tanpa bersikap seperti orang yang jijik melihat bangkai.
Memang tidak dijelaskan Herge, mengapa koran mengutip iklan untuk membiayai produksi. Sebab semua orang jelas memahaminya. Tanpa iklan, informasi itu akan menjadi terlalu mahal dan publik hanya akan memperoleh terlalu sedikit informasi yang menjadi haknya. Memang cost of burden tidak pantas dibebankan kembali pada publik, yang sudah bayar pajak, bayar retribusi, dan membeli semua barang dengan harga pasar, melainkan pada lembaga-lembaga yang mengambil keuntungan dari publik. Das ist Das. Setiap langkah wartawan sebagai wartawan, harus memberi manfaat bagi publik maka menjadi relevan jika cost of burden-nya berasal dari lembaga yang selama ini mengambil manfaat dari publik dan mau mendonor. Jika Tintin meminta sumbangan pada Rastapapoulos sang pengusaha untuk memperbaiki genting rumah-nya mumpung sekarang musim Halodo, atau membeli cadeau karena Snowy sang anjing kesayangan Jaarig hari ini, itu adalah urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan kewartawanannya.
Sayangnya, ada teori yang mengatakan, etical constraint sang pribadi akan berhubungan dengan profesional quality-nya. Mungkin teorinya yang salah, atau saya yang terlalu bego untuk mengingatnya. Tapi saya suka Tintin.
Jika saja Herge hidup hingga 100 tahun lebih, mungkin ia masih sempat menambah satu lagi koleksi serial komik Tintin ciptaannya, dengan kisah yang sad ending, ketika akhirnya Tintin harus mati terbunuh. Mungkin. Atau masih akan ada 100 kisah lagi menyusul. Tapi waktu rupanya hanya mengijinkan Herge menyelesaikan beberapa lembar saja, halaman pertama edisi terakhir yang diberi judul oleh penerbitnya Lotus Biru, sebelum wafat.(Nursyawal, Ketua AJI Bandung dari milis AJI-ajisaja@yahoogroups.com).
Majelis Hakim Yang Mulia,
Silakan saja Jaksa menuding saya menyebarkan berita bohong. Itu haknya sebagai penuntut umum untuk mencari-cari kesalahan orang sesuai keinginannya.Tapi saya tegaskan, kalau saya mau bohong buat apa melalui Majalah TEMPO, pendaringan saya, dimana saya membeli saham, dan memiliki saham dalam perusahaan itu. Saya bisa membuat banyak buletin terbitan atau selebaran tanpa nama, dengan berita yang lebih heboh, yang datanya mudah dicari, tanpa perlu cover both sides, atau konfirmasinya bisa dicari-cari pula. Bagi saya soal kebakaran Tanah Abang, adalah soal berita yang layak ditulis, kalaupun saya mendapatkan berita yang lebih dari sekadar berita, mungkin suatu keberuntungan saya atas usaha yang saya lakukan.
Untuk Kepentingan Umum
Kenapa Tanah Abang?
Saya sangat mengenal Tanah Abang. Sejak saya lahir (tahun 1965), orang tua saya sudah tinggal di Jalan Kebon Pala I, Kelurahan kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan berdasarkan cerita almarhumah nenek saya, Zahra binti Abubakar bin Muhammad Alhabsyi, ayahnya (Abubakar Al-Habsyi-kami menyebutnya jid Bakar) adalah salah seorang yang membangun masjid Al-Ma'mur, Tanah Abang sekitar tahun 1900. Dua Juli (2004) lalu Masjid ini dikunjungi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk shalat Jumat. Bahkan, beberapa pekan kemudian calon wakil Presiden Kiai Hasyim Muzadi melakukan hal yang sama. Beliau-beliau pula (Abubakar bin Muhammad Al-Habsyi dkk) yang membangun sekolah Jamiat Kheir dan Panti Asuhan Daarul Aitam yang tak jauh dari Masjid Al-Ma'mur.
Menurut ibu saya, kakeknya Jid Bakar itu, punya mertua Habib Alwi Alhabsyi yang kawin dengan perempuan Betawi, nenek saya menyebutnya Nyak Mune (nama aslinya Maimuna). Saudara-saudara Nyak Mune inilah adalah jawara-jawara Tenabang, antara lain Sabeni (ibu saya menyebut Kong Ni). Bahkan, kata ibu saya, saat ia masih perawan (gadis), kalau mau nonton bioskop secara gratis diloloskan oleh Kong Ni. Selain guru silat, belajar ngaji, Kong Ni juga adalah penjaga/centeng bioskop Surya.
Yang saya ingat, saat saya pertama kali sekolah sekitar tahun 1971, saya disekolahkan di Sekolah Dasar Tionghoa. Guru-gurunya kebanyakan orang Cina, yang sangat baik sekali. Pada masa itu setiap pagi masuk sekolah diberi segelas susu di gelas alumunium dan sepiring bubur kacang ijo. Murid-murid kelas kami campur dari berbagai suku dan ras. Di belakang sekolah saya terletak, toapekong-tempat persembahyangan orang-orang Tionghoa, pemeluk agama Khonghucu. Saya masih ingat betapa hiruk pikuknya sekolah kami saat mau dibongkar pada tahun 1972, karena mau dibuat pasar. Di tengah hiruk pikuk itu bahkan saya masih ingat, mendapat uang kertas Rp 1.000 di bawah lapak pedagang paku, saat pulang sekolah. Duit segitu pada masa itu sangat besar sekali.
Akhirnya sekolah kami dibongkar dan para murid cerai berai ke berbagai sekolah, ada yang ke SD Hati Suci di kawasan Kampung Bali, ada yang ke sekolah dasar lainnya. Saya dipindahkan orang tua saya ke SD Spoor Lama pagi I (sekarang SDN 1 Kebon Melati) di jalan Lontar, kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang. Di SD sebelumnya di Tanah Abang, saya termasuk murid yang biasa-biasa aja, tak masuk rangking. Namun, setelah pindah ke SDN Spoorlama, saat kelas III, saya menjadi yang terbaik saat itu. Saya jadi ingat, Pak Guru laki-laki Tionghoa yang mengajar dengan disiplin membuat saya jadi 'lebih' saat pindah ke sekolah lain. Terima kasih pak.
Ibu saya, kakak-kakak saya, dan bekas tetangga dulu yang dekat dengan keluarga kami, tentu masih ingat kalau saya ngambek, mereka bisa menemukan saya tidur dan menginap di Masjid Al-Ma'mur. Namun, setelah ada Pasar Tanah Abang, bukan hanya Masjid Al-Ma'mur tempat saya bermain, tetapi juga Masjid di atap Pasar Tanah Abang, yang banyak anginnya. Tentu saja saya tak pernah menginap di masjid pasar itu. Di halaman parkir pasar di lantai yang tak jauh dari masjid, kalau malam, juga jadi tempat latihan karate, saya sempat berlatih beberapa bulan di tempat itu, lalu berhenti karena bosan.
Saya ingat tetangga-tetangga saya kebanyakan berasal dari Sumatera Barat yang berdagang di Pasar Tanah Abang. Bahkan tetangga sebelah rumah, yang ibunya teman baik ibu saya,anak-anaknya juga teman-teman kami yang sepantar, meninggalkan bisnis pembuatan kerupuk kulit (bahasa Padangnya kerupuk jangek, bahasa Jawanya, ramba') lalu berdagang tekstil di Blok A. Orang-orang Sumatera Barat tetangga saya yang berdagang di Pasar Tanah Abang, sukses dan maju. Mereka membangun rumah yang bagus, bahkan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi mereka masih tetap sederhana, ibu dan anak-anaknya kerap saya temui masih menjaga kios mereka di pasar itu (sebelum kebakaran). Jika saya berkunjung di tengah kesibukan mereka, saya ditawari makan sate padang dan minum teh botol.
Banyak teman-teman SMP dan SMA saya punya kios di Pasar itu. Walaupun mereka sudah menjadi sarjana, mereka tak minta-minta pekerjaan menjadi klerk pemerintah, mereka tetap menjadi pedagang di Tanah Abang. Adik-adik dan kakak-kakak perempuan saya termasuk langganan yang membeli pakaian jadi, sprei (untuk dipakai atau dijual kembali) atau tekstil kiloan untuk celana, baju atau bahan kain untuk hordeng. Tante-tante saya, saudara-saudara saya dari Surabaya, dan Kalimantan, kerap datang ke Jakarta kulakan di Pasar Tanah Abang, terutama dua atau tiga bulan menjelang lebaran (Idul Fitri) untuk menjual kembali di kota-kota tempat mereka tinggal.
Jadi ketika, terjadi kebakaran di Pasar Tanah Abang, yang pertama saya pikirkan, apakah kebakaran itu sampai merambat ke tempat tinggal ibu saya? Saya langsung telepon ke rumah ibu saya, tapi aman. Lalu saya tanya apakah ada diantara keluarga kami yang sedang berbelanja ke sana? Saya juga ditelepon teman SMP dan SMA saya yang kiosnya ikut terbakar. Saya langsung menuju lokasi saat kebakaran terjadi. Melihat api, asap tebal, dan teriakan orang melolong, menjerit-jerit dan menangis membuat saya bersedih. Kenapa hal seperti ini sering terjadi? Kenapa api tak mudah dipadamkan dan begitu cepat melalap pasar itu?
Saya sedih, harga kos yang mahal, berbagai pungutan yang para pedagang bayar ke pada para petugas PD Pasar Jaya atau Kepala keamanan Pasar, tetapi tak bisa membantu banyak saat sijago merah ngamuk. Air dihidran seolah mampet tak mau keluar, selang mobil brandweer seolah tak mampu menjangkau titik-titik api.
Karena itulah tulisan pertama, setelah kebakaran angle (sudut pandang)-nya ketidakmampuan aparat pemerintah/pengelola pasar menjaga kepentingan publik. Fasilitas umum seperti tak berfungsi. Saya berbicara dengan para korban kebakaran (mereka kebanyakan adalah pedagang, bukan preman yang hanya mengutip uang/memalaki pedagang). Saya berbicara pada banyak orang, termasuk para tetangga dan teman-teman saya yang kiosnya habis terbakar, yang barang-barangnya dilumat api tak bisa diselamatkan lagi, karena bahan yang mudah terbakar itu.
Dua halaman yang saya tulis pada edisi 24 Februari-2 Maret 2003, tak cukup untuk menulis tentang kisah sedih kebakaran Tanah Abang. Karena itu juga TEMPO mem-follow-up-i tulisan pada edisi berikutnya, mengenai pihak-pihak yang mendapat keuntungan setelah Tanah Abang terbakar. Mohon maaf, sebenarnya soal keuntungan dari kebakaran itu, jangan diartikan secara negatif. Dalam kehidupan di dunia itu hal biasa, ada orang yang mendapat keuntungan dari musibah. Sebagai contoh, ada orang yang mati, keuntungan bagi penjual kembang, atau penggali kuburan. Ada orang yang sakit juga keuntungan bagi para dokter, klinik atau rumah sakit, Begitu juga setelah ada kebakaran, ada pemulung yang beruntung dari hasil pulungannya, ada pengusaha yang juga untung karena mendapat proyek untuk membangun kembali. Apalagi soal rencana renovasi sudah terdengar lama sebelum kebakaran (Bahkan diakui oleh Direktur PD Pasar Jaya, Syahrial Tanjung dalam kesaksiannya di pengadilan tempo hari dan juga anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Dani Anwar).
Syahrial Tanjung bahkan sudah mempresentasikan cetak biru proyek itu pada DPRD DKI. Dalam boks, tulisan dua halaman (edisi 3-9 Maret 2003) itu juga ditulis rentetan kerugian setelah Pasar Tanah Abang terbakar. Bukan hanya para pedagang di Pasar Tanah Abang, tetapi juga pedagang batik dan kain di Pekalongan, pemasok baju bordiran dari Tasikmalaya, pemasok tekstil dari Majalaya, Bandung bahkan pedagang-pedagang asal Afrika yang biasa mengirim barang-barang sandang itu ke negerinya. Jadi tulisan itu benar-benar melihat sudut untuk kepentingan publik, agar tak ada lagi pedagang yang dirugikan, karena setelah dibangun mereka tak mampu mendapat atau membeli kios, karena mahalnya. Karena pembangunan kembali sebuah pasar yang terbakar, berdasarkan pengalaman para pedagang tak berpihak kepada mereka. Tetapi berpihak kepada pemilik-pemilik modal dan uang. Silakan bapak-bapak hakim amati dari kejadian, lewat televisi, dan media massa, bagaimana para pedagang Pasar Tanah Abang sampai sekarang masih protes soal kepentingan mereka yang diabaikan pemerintah DKI atau PD Pasar Jaya.
Karena itu selain mereka protes melalui sejumlah pertemuan dengan pemerintah, pihak PD Pasar Jaya, DPRD, suara mereka disalurkan lewat media massa. Sampai sekarang saya masih diundang saat mereka rapat menentukan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Saya hanya bisa mendengar dan mencatat apa yang mereka lakukan. Jika saya berniat menulis, baru saya mewawancarai kembali dan mengorek keterangan lebih jauh sesuai dengan angle tulisan untuk media massa tempat saya bekerja.
Itulah seputar Tanah Abang dan pekerjaan saya. Saya kini tentu saja dirugikan, terutama waktu yang termakan oleh sidang-sidang pengadilan, tak banyak yang bisa saya ungkap karena persoalan ini. Tapi saya nikmati saja deh. Tapi di samping saya yang dirugikan, mungkin juga ada keuntungan pada orang-orang lain yang kini mendapat berkah karena dibayar mahal sebagai pengacara Tomy Winata, atau jurnalis-jurnalis, aktifis-aktifis, preman-preman, aparat bahkan sekelompok orang Tanah Abang yang mendapat keuntungan dari konflik ini.
Bagi saya ini sebuah catatan sejarah. Seperti saya telah katakan pada eksepsi saya terdahulu, putusan apapun yang akan hakim jatuhkan saya akan hadapi. Saya sudah punya pengalaman dengan penguasa dahulu yang menindas, yang menghukum saya lewat tangan para hakim di pengadilan negeri sampai Mahkamah agung dengan hukuman penjara 3 tahun. Bahkan saya dipindah-pindahkan ke beberapa penjara mulai dari Salemba, Cipinang, Cirebon sampai kuningan, Jawa Barat karena saya masih tetap menulis dari dalam penjara. Bahkan saking ketakutannya Kepala penjara Cirebon tak mengizinkan saya keluar penjara menjenguk ayah saya yang meninggal. Itu sudah nasib saya, karena tanpa menjenguk jenasahnya terakhir kali saya masih bisa mendoakannya hingga kini. Insya Allah, bila doa saya tulus, akan sampai dan diterima Allah, apalagi bila saya iringi dengan Shalawat...3 kali. Belakangan penguasa penggantinya, Presiden Bachrudin Jusuf Habibie, memasukan nama saya dalam daftar yang harus diberi amnesti. Jadi, kalau Jaksa memasukkan klausul untuk memberatkan saya, karena pernah dihukum jadi keliru.
Kenapa keliru? Ada dua alasan, pertama Presiden Habibie memberi amnesti, artinya, Presiden yang baru menyadari kesalahan pemerintah yang terdahulu (termasuk jaksa sebagai aparat pemerintahnya) karena pemenjaraan itu. Kalau saya mau saya bisa menuntut rehabilitasi (pengembalian nama baik dan sejumlah penggantian atas kerugian yang saya peroleh selama di penjara). Kalau mau seperti para korban tragedi Tanjung Priok mendapat rehabilitasi dan uang pengganti atas kesalahan pemerintah yang memenjaraannya. Tapi tak saya lakukan, biarlah jadi catatan sejarah saja. E..e....malah jaksa memasukkan sebagai alasan pemberat (padahal seperti eksepsi yang pernah saya bacakan), saya sudah cerita Jaksa yang menyeret saya ke penjara, memohon maaf atas nama pribadinya saat saya ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dua tahun yang lalu.
Alasan kedua, kalau penjara dianggap sebagai tempat menjalankan kesalahan yang pernah dilakukannya. Tentu ini seperti penebusan dosa, setelah orang itu sudah menjalankan kewajibannya, sudah bersih pula saat ia sudah keluar. Jangan dikira, bapak-bapak yang berada di luar ini bukan orang yang tidak pernah bersalah. Justru bapak-bapak ini orang yang paling berbahaya, korupsi, memeras orang dan perbuatan nista lainnya, tapi tak pernah masuk penjara atau diadili.
Sudahlah boleh banyak orang bisa dibeli, tapi saya masih bisa membelikan Tomy bunga crysan putih, walaupun cuma sekuntum. Sekaligus menandakan, bahwa kami kaum jurnalis bukanlah musuh anda, kalau anda merasa sebagai musuh ya, terserah, tak akan bisa kami paksakan. Sebagai jurnalis kami tetap akan menulis, memberitakan informasi kepada masyarakat dari manapun sumbernya, bahkan dari orang-orang yang membenci kami para kaum jurnalis.
Majelis Hakim Yang Dibanggakan,
Soal bantahan Tomy Winata saat memberi kesaksian di Pengadilan TEMPO hari atau juga pejabat lainnya terserah saja. Soal bohong, kan, urusannya dengan Tuhan. Tentu Tomy, seperti saat bersaksi juga punya Tuhan. Karena majelis hakim, atau penegak hukum lainnya toh, tak mau menindaklanjuti. Walaupun ada aturan hukum yang menyuruhnya untuk menindak bila ada kesaksian bohong.
Profesor.Floyd G.Arpan dan Drs.S.Rochady dalam buku Wartawan Pembina Masyarakat menulis : Suatu hal yang harus tetap diingat ialah, bahwa pejabat resmi pemerintah atau para pedagang besar, biasa dengan amat mudah memungkiri saja apa yang pernah dikatakannya dan membiarkan wartawan dengan segala upaya mempertahankan diri dalam ketidakpercayaan orang. Umumnya pejabat pemerintah itu membiasakan diri memungkiri apa yang pernah dikatakannya bila ternyata keterangannya itu membuat rakyat jadi gelisah atau mengakibatkan gengsi pejabat itu sendiri merosot karena keterangannya sendiri.(Bina Cipta, Jakarta 1988, hal.38)Saya yakin saksi-saksi yang bersaksi di pengadilan untuk kasus ini kebanyakan tak baca komik Tintin. Kecuali saksi-saksi yang diajukan pengacara kami. Misalnya, saksi-saksi fakta yang diajukan Jaksa, menurut pengakuannya di Pengadilan bukan lah orang yang suka baca. Haji Roni Syahroni, baru sekali baca Majalah TEMPO, karena ada yang memberitahu bahwa ada tulisan tentang Tomy Winata di Majalah TEMPO yang berkaitan dengan kebakaran di Tanah Abang, Ibrahim bin Muhammad Tohir, cuma baca dua alinea dan langsung emosinya meledak, Abraham Lunggana alias Lulung, yang baru beli majalah TEMPO pada tanggal 8 Maret 2003, setelah diberitahu Ucu, padahal calon anggota legislatif yang gagal maju itu, menurut pengakuannya tidak suka baca koran dan majalah. Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu bahkan tidak pernah baca sama sekali majalah.
Bagi saya ini menimbulkan pertanyaan Buat apa dan kepentingan siapa mereka menjadi saksi? Lucu semua saksi fakta itu seolah-olah menjadi pembaca yang aktif bahkan partisipatif setelah Ada Tomi di ‘Tenabang’? Bagaimana dengan tulisan saya yang pertama sepekan sebelumnya, yang masih berkaitan dengan kebakaran Pasar Tanah Abang?
Untuk jadi saksi yang bisa mengantarkan orang masuk penjara, saja gak baca serius, apalagi baca Tintin. Mana sempat? Udeh-lah abang-abang itu jangan mikirin duit melulu. Kartu abang-abang ane tau. Janganlah nyusain pedagang Tenabang. Uang yang sekarang diperoleh disyukuri dan dinikmati aje, jangan kemaruk. Malah sekarang belaga ikut-ikutan ngurusin blok B,C,D, dan E yang mau dibongkar Gubernur Sutiyoso. Mendingan ente bikin jaringan perpustakaan anak-anak di daerah ente. Biar anak-anak jadi pinter, jadi calon legislatif yang berkualitas (kayak Dani Anwar anak Kebon Pala I dari PKS-Partai Keadilan Sejahtera, juga saksi dalam kasus ini). Jaman jawara-jawara ude lewat, bang. Sorry ye bang Ane gak sedikitpun takut ame ente. Ane cuma takut sama Allah dan ame Umi ane.
Majelis Hakim,
Asal usul saya mendapatkan informasi untuk tulisan ini sudah saya jelaskan saat keterangan terdakwa. Silakan baca hasil catatan panitera yang baik hati dan tidak sombong. Soal putusan, mah, sekarang terserah majelis hakim. Kebetulan anda sekarang diberi amanat dengan atas nama Tuhan untuk memutuskan. Apakah anda akan menggunakan amanat itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang banyak, atau akan mengkhianati amanat itu. Semua nya terserah hati nurani anda. Toh, bukan sekali ini anda memutuskan perkara. Apalagi ini bukanlah perkara besar yang sulit bagi anda. Ini persoalan kecil, yang memang mendapat liputan media massa, karena para terdakwanya adalah para jurnalis, dan disatu sisi ada orang yang ‘kebakaran jenggot’, begitu istilah saksi Lulung. Yang 'kebakaran jenggot' yang dimaksud Lulung adalah Tomy Winata, pengusaha besar yang banyak koneksi dimana-mana. Bahkan juga punya media massa mulai dari Koran, Majalah, Radio, dan TV yang akan dilaunching beberapa bulan ke depan. Bahkan kalau omongan David Tjioe alias Amiaw benar bahwa dia mengeluarkan Rp 150 juta untuk wartawan yang mereka punya listnya, tak salah kalau kasus ini mendapat perhatian besar.
Karya jurnalistik, yang kini diadili secara pidana dan perdata, tentu menarik perhatian. Di PN Jakarta Selatan, karikatur seorang yang sudah dihukum sampai tingkat banding, dibela oleh hakim sebagai penghinaan, sebuah kemunduran, begitu juga soal judul-judul di Harian Rakyat Merdeka, yang membuat seorang redaktur pelaksana dihukum pidana dengan hukuman, hanya karena ada judul Mulut Mega Bau Solar. Apakah itu pengertian asli, kutipan seorang sumber atau kiasaan karena harga solar yang melonjak tinggi waktu itu. Bahkan hakim yang memutus belum pernah menguji bau apakah mulut mega itu, apa benar bau solar, bau pom bensin, bau minyak wangi, atau bau naga?
Tak Ada Niat atau Sengaja Menghina/Unmalice
Kembali ke soal Tomy Winata, saat saya menulis, tak pernah selintas sedikitpun, perasaan mau menghina, menista, mencemarkan nama baik atau menfitnahnya. Yang terjadi saya mendapat informasi lalu mencoba mengkonfirmasi semua berita itu. Kalau ingin menghina buat apa saya meminta para reporter mengkonfirmasikan masalah itu ke Tomy Winata. Tulis aja. Toh hasilnya akan sama saja. Kalau akibat tulisan itu Tomy mengeluarkan seluruh kekuatannya, pasukannya, uang yang dimilikinya, aparat koneksinya untuk menjerat saya secara pidana maupun perdata. Saya umumkan, cacing sekecil apapun kalau diinjak akan menggeliat. Apalagi saya yang bukan cacing, punya darah, tulang, tangan, mata, kaki, telinga dan otak.
Memang setiap manusia mempunyai rasa takut. Menurut para psikolog perasaan takut ketika menghadapi bahaya senantiasa berjalan beriring dengan manusia sepanjang hidup hingga saat kematiannya (Hasan Shaffar, Takut : Analisis Psiko-Religius Terhadap Phobi, Stoa, 2003, hal.39). Rasa takut hanyalah salah satu unsur mekanisme yang melengkapi kejiwaan manusia dalam usahanya untuk membetengi diri ketika mendapati berbagai macam bahaya dari luar maupun dari dalam, agar dirinya berusaha mengatasi bahaya yang mengancam keselamatannya.
Rasa takut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena tanpa memiliki rasa takut, manusia tidak akan memiliki upaya dan tidak menggunakan nalarnya untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya, kesulitan atau rintangan. Tanpa rasa takut, manusia tidak akan mempersiapkan dirinya dengan kepastian keputusan dan upaya-upaya pencegahan untuk keselamatannya. Imam Ali bin Abi Thalib berkata,"Siapa yang takut, Aman!" Rasa takut yang ada pada setiap manusia pada dasarnya merupakan aset yang positif. Namun, jika rasa takut melebihi porsi yang seharusnya, tentu saja justru akan berdampak negatif terhadap dirinya. (idem hal 40-14).
Ibu saya pernah menyarankan saya untuk tak lagi jadi jurnalis, "cara pekerjaan lain, atau jual korma deh di pasar, si anu (dia menyebut nama seseorang) udah bisa bikin rumah dari jualan korma." Mungkin menurutnya, penghasilan jual korma lebih banyak daripada menjadi jurnalis. Namun, saya menjelaskan kepada ibu saya, semua pekerjaan adalah baik asalkan halal cara mendapatkannya, tetapi yang paling baik adalah mau mempertahankan haknya.
Saya bilang pada ibu saya, semua pekerjaan menanggung resiko. Kalau saya berdagang korma, lalu dipalak preman pasar, tetapi saya melawan. Karena saya ribut dengan preman yang memalak saya itu, dan ditusuk yang menyebabkan luka atau mati. Saya juga akan ditangkap polisi dan mungkin ditahan. Bahkan dagangan saya juga bakal diobrak-abrik teman-teman preman itu. Tapi saya sudah mempertahankan hak saya. Begitu pekerjaan saya sebagai jurnalis sekarang. Saya memberitakan informasi apa adanya adalah kewajiban saya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu. Ibu saya mengerti penjelasan saya tersebut. Jadi punten aja Tom! saya mah gak takut walau anda ancam dengan menggunakan preman, seperti yang terjadi 8 Maret 2003 lalu saat menyerbu kantor kami rame-rame. Walau pun anda dibantu polisi, jaksa atau aparat penegak hukum lainnya.
Majelis Hakim,
Sebenarnya saya ingin kayak Tintin dalam komik ciptaan Herge. Karena masalah Pasar Tanah Abang (lebih enak kawasan Tanah Abang, karena tak lagi menyangkut soal pasar) kini berkembang sudah semakin jauh, bahkan lebih hebat dan uang yang beredar sudah belasan kali lipat dari yang saya tulis dan informasi yang saya peroleh dulu. Bahkan kebakaran sudah terjadi di RW, yang tak jauh dari rumah ibu saya. Saya yakin bakal terjadi kebakaran-kebakaran lain, terutama di pemukiman warga yang padat, di sekitar Waduk Melati, di belakang bekas Hotel Kartika Plaza. Tanda-tandanya sudah terasa, kalau anda hidup di kawasan itu.
Saya ingin seperti Tintin, karena saya tahu banyak informasi, soal perdagangan obat-obatan, judi, penjualan perempuan, penguasaan tanah secara kasar dan tak manusiawi, penyelundupan bibit pertanian ilegal di Kendari, usaha pelelangan ikan di Tual, yang semuanya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kalau saja saya komikus seperti Herge dan bukan bekerja di media berita saya bisa lebih bebas, menuangkan informasi yang diperoleh, tanpa perlu konfirmasi. Sayangnya saya bukan Tintin atau Herge, si penciptanya.
Saya ini seorang jurnalis, menulis atas dasar informasi yang layak diketahui masyarakat. Seperti dalam butir pertama kode etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI yang 7 Agustus kemarin berulang tahun ke-10) yang juga diterima menjadi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI-Surat Keputusan Dewan Pers No.1 tahun 2000) "Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar". Dengan informasi yang saya peroleh itulah, juga sesuai etika jurnalistik dan standar profesional, melakukan konfirmasi (meliput dari dua sisi-cover both sides).
Kalau semua informasi yang diperoleh jurnalis, dianggap perbuatan kriminal karena tak memiliki bukti tertulis dan tak mau menyebut sumbernya, media massa cetak bakal cuma jadi lembaran putih. Atau anda lebih suka dengan desas-desus, gossip atau selebaran gelap, yang tak perlu konfirmasi? Jangan sampai, deh, kami, warga negara tak percaya lembaga peradilan ini, karena ternyata ini institusi cuma untuk orang berduit, berkuasa dan kuat. Dalam kasus, Majalah TRUST dengan Tersangka John Hamenda yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga, ada bukti tertulis audit BNI dan saksi di pengadilan mengakui bukti itu, tetap saja Majalah TRUST dikalahkan. Ooo, come on! Sudahlah jangan main-main dengan keadilan, bencana akan segera datang kepada anda sekalian kalau keadilan dipermainkan, hanya untuk keuntungan diri sendiri dan suatu masa saja.
Kalau saja saya seorang anggota legislatif atau pejabat pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini, saya akan mengusulkan segera dibuat Undang-undang Kejahatan Terorganisir dan berlaku surut. Agar para pengusaha tak bermoral yang berkolusi dengan polisi atau aparat penegak hukum lainnya bisa diseret ke pengadilan, bahkan, kalau perlu dihukum tembak seperti para penyelundup dan pengedar narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Sayang, seorang jurnalis di negeri ini untuk melindungi diri sendiri saja tak mampu, walaupun ada Undang-undang (tentang Pers No.40 tahun 1999) yang menjaminnya.
Kasian deh LU!
Wassalam.
Jakarta, 30 Agustus 2004
Ahmad Taufik