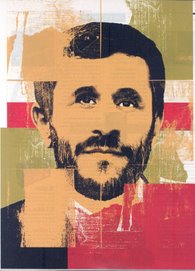Niat memilih dalam pemilihan umum 2009, sudah bertekuk dalam hati, tak bisa lagi diganggu. Memang sejak kejatuhan Soeharto, rezim penindas yang berkuasa selama 32 tahun, aku sudah bertekad untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, minimal ikut memilih.
Namun, karena suatu keperluan, pada saat pemilihan aku akan memilih di luar kota, tepatnya di luar dari pulau tempat aku tinggal selama ini. Karena tekad itulah aku mengurus, surat untuk pindah memilih ke sebuah tempat pemungutan suara di sebuah desa yang tak kukenal.
Sepekan menjelang pemilihan, aku telah mengantungi surat pindah memilih, dari panitia pemilihan di kelurahan tempatku berdomisili. Modal itulah yang membuatku gembira menggunakan hak sebagai warga negara, memilih. Walaupun, tentu saja boleh aku tak menggunakan hak itu, karena ada hak juga untuk tidak memilih.
Nah, sesampai di luar pulau, tiga hari menjelang pemilihan, surat pindah memilih itu ku berikan pada seorang yang memang tinggal di daerah pemilihan tersebut. Tempat yang bakal aku tinggali, dia juga salah seorang calon wakil rakyat untuk provinsi itu.
Kami, berempat tinggal di rumahnya sehari menjelang pemilihan. Karena, pemilihan akan dilakukan pagi-pagi. Aku dan seorang kawan memiliki surat pindah memilih, sedangkan dua orang lainnya, tak punya. Pagi-pagi sejam menjelang pemilihan, sang tuan rumah memberikan empat pucuk surat panggilan untuk memilih.
Tak ada nama ku dan nama temanku yang sudah punya surat pindah memilih. “Lo, kok, bukan nama kami?”kataku.
“Udah gak papa, pake aje, ribet ngurusnya,”ujarnya.
Herannya lagi, temenku dua laki-laki, yang tak punya surat pindah memilih, juga mendapat surat panggilan. “Sekalian, kamu juga milih ya,”ujar sang tuan rumah.
Setengah jam, setelah waktu memilih mulai. Aku berangkat ke tempat pemungutan suara, yang hanya sepelemparan batu, dari rumah tempat aku menginap. Kulihat seorang temenku, sudah duduk di dalam lingkaran tali menunggu panggilan mendapat surat suara. Dengan sedikit lagak, aku melihat-lihat daftar calon wakil rakyat yang akan ku pilih. Tak ada yang ku kenal betul, hanya ada tiga orang, seorang calon wakil rakyat untuk pemilihan pusat, satu seorang senator dan seorang lagi ,ya, calon tempat aku tinggal.
Aku, masuk ke gelanggang, dengan surat panggilan atas nama orang lain. Hati berontak, namun aku mencoba pengalaman baru ini. Surat panggilan atas nama seorang haji ku berikan pada panitia. Salah seorang diantaranya berbisik pada temanya, “ia kenal nama itu, dan orangnya bukan yang ini.” Aku tampaknya menjadi pembicaraan mereka. Namun, orang-orang sang tuan rumah yang juga calon wakil rakyat sudah “membereskannya.”
Memang tak enak hati. Tapi aku berlagak bodoh, seolah tak tahu menjadi bahan pembicaraan mereka. “Secara prosedural, toh, aku sudah memberikan surat pindah memilih dari daerah asal,” demikian hatiku membenarkan. Cuma mungkin ini jalannya, untuk memperoleh hak memilih. Mungkin menindas hak pilih pemilik surat panggilan itu, atau nama itu memang tak ada, aku tak tahu, malah tak mau tahu. “Orang itu, gak ada disini kok,”kata seseorang, “orangnya” tuan rumah, menenangkan perasaan “tak enak: yang terpancar dari raut mukaku.
Nama, “Haji Abdul Halim!”suara keras memanggil. Aku tergagap, o, ya, itu “namaku”. Aku maju menerima empat pucuk surat suara. Entah mata di luar gelanggang dan panitia pemilihan setempat, menatapku, apa pula pikiran mereka, aku acuh saja. Menuju bilik pilih yang terbuat dari kain (jarik) batik bekas, dengan tiang bambu. Dari empat bilik hanya satu yang kosong.
Besarnya surat suara, dan bayangan kesulitan melipat kembali, aku mencari jalan yang mudah, buka separuh, dan mencoret (bukan mencontreng, itu lebih mudah), nama yang sudah ada dalam pikiranku. Tiga pilihan seperti yang ku kenal tadi, dan salah satu pilihan di calon wakil rakyat tingkat dua, sekadar aku coret sesuai nomor yang sama dengan pilihan pusat dan provinsi. Ambil jalan mudah, walau tak kenal siapa dia?
Kemudahan berlanjut saat memasukkan surat suara. Tak ada himpitan lubang kecil, seperti celengan, tapi hanya sebuah boks besi milik komisi pemilihan umum, yang sudah terbuka bagai kaleng blek. Hanya mengepaskan warna surat suara dengan warna kaleng blek itu, plung!
Melangkah keluar, sang tuan rumah sambil menggendong anaknya, segera menggiringku pulang ke rumahnya. Huff, selesai, memilih. Walau hati mau galau, tak nyaman dengan cara itu. Perasaan yang sama, juga terjadi pada seorang kawanku yang selesai memilih juga dengan nama panggilan orang lain.
Waktu terus berlalu, mata hari semakin menyengat, sang surya menampakkan keperkasaannya. Dua orang kawanku yang tak punya surat pindah memilih, tapi diberikan surat panggilan untuk memilih oleh sang tuan rumah. Salah satu surat panggilan itu, bernama Saraiya. Kami menduga itu nama seorang perempuan. Semula, aku sudah memberi saran untuk tak mengambil kesempatan itu. Entah angin apa yang membawanya ke gelanggang, tempat pemungutan suara.
Sempat ragu, karena di tempat itu ada beberapa keributan soal orang yang tak dapat surat panggilan memilih. Temanku, menyerahkan surat panggilan, dan masuk dalam lingkaran tali menunggu bersama penduduk setempat lainnya, panggilan mendapat surat suara. Gaya dan pakaian sudah disesuaikan dengan penduduk setempat.
Dari loudspeaker keras terdengar :”Saraiya!” Ada panggilan, satu, dua kali, saat panggilan ketiga, kawanku itu berdiri, namun bersamaan dengan itu seorang nenek-nenek ikut berdiri, maju mengambil surat suara. Kawanku akhirnya, hanya berdiri dan membetulkan sarung menghilangkan grogi. Tak lama keributan serupa terjadi. Beberapa orang karena takut gagal memilih
Lalu kawanku yang berusia sekitar 25 tahun itu, pergi pelan-pelan ke luar gelanggang dan pulang ke rumah, tempat kami bermalam, takut kejadian yang lebih seram. Maklum ini kampung orang.. “Masak mau saingan dan rebutan ama nenek-nekek,”katanya kemudian.
Rupanya, “sang nenek” pemilik nama asli Saraiya (baca Saraiye), tak dapat surat panggilan memilih. Ia nekat ke tempat pemungutan suara mengetahui dan mencari haknya, dan mendapatkannya. Sang tuan rumah yang memberi surat pangilan itu kepada temenku, tak menduga nama dalam surat panggilan itu akan datang, mencari haknya yang hilang. (**)