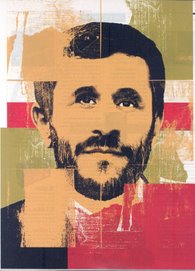Tak punya harapan lagi bertemu Olie, sudah seminggu dia tak pernah mengontak aku. Aku juga tak pernah melihatnya lagi di halte tempat pertama kali kami bertemu. Tiga hari setelah kegagalanku mengejar bis, pada jam yang sama aku mencoba menunggui dan mencarinya. Selama tiga hari, setiap hari mulai pukul 15.00, aku menunggu di halte itu, sampai menjelang maghrib, aku selalu pulang dengan tangan hampa.
Hari ke empat aku mulai mencoba melupakan Olie, aku kembali menekuni pekerjaanku, sebagai asisten pengacara dan menyelesaikan skripsi ku. Aku tak lagi pergi ke halte dekat Hotel Panghegar.
Tit…tit…tit…bunyi serantaku, tanda ada pesan masuk.
Aku tak lagi bernafsu, sudah seminggu ini, pesan seranta masuk cuma dari kantor atau teman kuliah. Aku baru saja usai makan, siang, lagi enak-enaknya mata tunduh. Apalagi angin sepoi-sepoi menambah nikmatnya hidup kalau bisa selonjoran di sofa, lalu tertidur sampai azan ashar, setelah itu menyeruput kopi, oooh.
Dengan mata tinggal separuh aku pencet tanda baca pesan dalam seranta ku. “Temui aku, di halte biasa pukul 16.30, jangan nggak!”
Yihuiiii! Aku terlompat kegirangan.
Mata tak lagi tunduh, pikiran segera kembali. Wajah Olie muncul terus dalam benakkku. Dada terasa deg-degan menunggu waktu yang dijanjikan Olie untuk bertemu. Saat itu juga aku langsung masuk ke kamar mandi, mengosok-gosokan sabun ke seluruh badan, dan lebih lama di bagian yang paling sensitif, keramas dan bercukur. Aku shalat zuhur dengan riang, dalam bacaan shalat selalu terbayang wajah Olie, begitu juga rukuk dan sujud, mulutku terus komat-kami menyebutkan rasa syukur.
“Alhamdulillah, terima kasih ya, Allah, kamu temukan lagi aku dengan Olie!" Gumamku dalam hati.
Pukul 15.00 aku sudah di halte itu, aku memastikan diri tak telat, lebih baik menunggu satu setengah jam, daripada pikiran jadi gak keruan selama seminggu. Untuk mengusir rasa bosan aku membaca buku yang ku bawa dari rumah “The sexual Wilderness” karangan Packard.
Inginnya mendapat informasi sambil menunggu, malah wajah Olie terus terbayang dalam lembaran-lembaran buku itu. Menunggu satu setengah jam, terasa lama sekali, tiap dua menit mataku menengok kiri kanan, aku tak tahu di mana letak kantor Olie sebenarnya di kiri atau di kanan halte, atau malah di seberang jalan. Tapi aku yakin, kali ini aku akan bertemu Olie.
Benar saja lima menit kurang dari waktu yang dijanjikan perempuan manis dengan rambut tergerai , tubuh dibalut terusan warna putih sedikit di bawah lutut. Sebagai sekretaris Olie cukup berpenampilan sopan, biasanyanya seorang sekretaris, minimal memakai rok di atas lutut. Namun melihat betis Olie saja, lelaki bisa dibikin bernafsu.
Dari kejauhan wajahnya tampak riang, tetapi setelah beberapa meter dan ia melihatku ia mencoba menyembunyikan senyumannya dengan wajah cemberut. Tapi aku tahu ia sedang berpura-pura cemberut. Bukankah pesannya itu berarti dia ingin bertemu aku?
"Hallo Olie," ku sapa lebih dahulu memecah kekakuan.
"Hmmmm," dia cuma begitu.
"E, sorry ya minggu lalu, aku sampai sini cuma lewat lima menit, bis Damri-udah jalan. Maklum deh naik angkot kan gak bisa diprediksi, dia ngetem lama di BIP."
"Bohong, pasti udah ada janjian ama yang lainya, ya?"
Aku diam saja. Kuambil tangannya, ku genggam, dan ku remas, entah dari mana keberanian itu muncul. Olie diam saja, tak berontak, tak menolak dan tak berusaha melepas tangannya dari tanganku.
"Nggak usah naik bis ya, kita jalan aja sebentar cari angin."
"Ya, tapi jangan sampai masuk angin."
Wajah Olie tak lagi ditekuk. Senyum kembali menghiasi bibirnya. Benar tebakanku , memang tadi ia berpura-pura marah, tapi kini tak lagi.
Aku juga lagi senang, hatiku berbunga-bungan, ada cewek cantik bersamaku, udara lagi bagus, dan kantong juga lagi berisi.
"Kamu suka ice cream?"
"Boleh!"
Hanya sepuluh menit menyusuri jalan bungsu, di trotoar yang lebar, tepat di depan Hotel Istana, aku menyeberang jalan. Tak jauh dari situ ada tempat minum dan makan kue, Rasa. Aku pernah diajak oleh temanku. Tempat itu salah satu yang terbaik di Kota Kembang
Penulis Bondan Winarno di Koran Kompas (Minggu, 02 Desember 2001 :Jalansutra ; Nostalgia Bandung) pernah menulis tentang Rasa. “ Di Jalan Tamblong, masih termasuk dalam kawasan "segitiga Braga" ada sebuah restoran bistik yang dulu cukup terkenal. "Steakhouse Rasa", begitu namanya dulu, kalau saya tidak salah ingat. Pemiliknya adalah seorang perempuan Sunda cantik yang menikah dengan laki-laki kulit putih. Restorannya terdapat di dalam sebuah rumah-toko model Belanda - jauh menjorok ke dalam dari bagian depannya. Para tamu harus menunggu lama untuk makanan yang dipesan. Untungnya di situ ada buku-buku tamu yang sudah ditandatangani dan dibubuhi komentar ratusan tamu yang sudah datang sebelumnya. Makan di "Rasa" - pada waktu itu - selalu merupakan kenangan eksklusif yang menyenangkan.
Sekarang tempat itu sudah diubah total menjadi bakery merangkap café. Kita bisa beli berbagai kue lezat, atau duduk di situ sambil makan atau sekadar minum es krim. Menunya tidak sebatas steak atau spaghetti seperti di masa lampau, tetapi sudah diperluas mencakup berbagai hidangan Indonesia lainnya. Laksanya cukup enak di sana. Es krim Coconut Royale juga boleh dicoba. "
"Kamu mau minum apa?"
"Kamu?"
"Disini ada yang enak namanya Pinacolada."
"Apaantuh?"
"Campuran nanas, cocacola dan icecream mocha, rasanya seeedap deh, mau coba?"
"Iya deh."
"Pinacolada dua?"
"Kuenya?"
"Aku berdua saja sama kamu, aku gak kuat makan sendiri."
"Oke, aku pesan cake strawberry chese, kamu suka?"
Olie hanya mengangguk.
Aku tak mau melepaskan tangannya dari tanganku, ku remas-remas, seperti orang melepaskan rindu. Olie diam saja. Mulutku seperti kelu. Kami hanya bisa saling melepaskan rindu seperti itu.
Sampai minuman dan makanan datang, kami baru bisa bercakap-cakap lagi. Aku ceritakan pencarianku ke rumahnya setelah gagal mengejar bis.
"Aku masuk daerahmu, tanpa nama lengkap, tanpa alamat, tiga jam aku muter-muter gak juga ketemu. Masak aku musti teriak-teriak Olie….Olie…Bisa-bisa aku dituduh sedang jual minyak oli lagi, jarang-jarang kan, biasanya orang teriak minyak….minyak, jual minyak tanah."
Olie tergelak, dia menepuk-nepuk bahuku. "Ah, bisa aja kamu?"
"Akhirnya aku ketemu orang suci di situ."
"Siapa tuh?" Dia terpancing
"Santo Yusuf."
"Iiih, itu, kan, nama rumah sakit?"
"Iya, memang aku ketemu plang nama rumah sakit Santo Yusuf, dari situ aku menemukan jalan keluar."
Olie kembali tergelak, tak terasa dua jam sudah kami habiskan di Rasa.
"Kamu suka nonton gak?"
"Terserah kamu."
Aku segera membawa Olie menuju Plaza, bioskop yang biasa memutar film kungfu, film kesukaan aku. Walaupun dua kali ganti angkot, jarak dari Rasa ke Plaza cuma duapuluh menit.
"Kamu suka film mandarin?"
"Aku jarang nonton bioskop, gak ada waktu?"
"Oke, kita nonton film ini ya, aku tidak ingat judulnya, karena memang aku cuma suka bintangnya Wang Sun Chien, artis cantik asal Hongkong bergigi bajing."
Dua karcis bioskop di deretan belakang, sekantung pop corn dan dua coca cola. Aku membimbing Olie, karena film sudah dimulai sepuluh menit. Sambil merangkak dalam gelap sebelah tanganku memegang erat Olie. Tempat bagian belakang ketemu juga setelah dibantu senter penjaga bioskop. Mataku terus menatap layar, tangan Olie tetap dalam genggaman.
Sesekali mulut menunyah pop corn dan menyeruput coca cola. Setelah jagung berontak ludes, Tak ada lagi yang dikunyah, Tanganku semakin keras, meremasnya. Wajahku ku dekatkan ke wajahnya. Olie menengok, saat itulah ku sambar bibirnya. Kami saling melumat. Tanganku terus meremas, kini bukan lagi tangan, tapi sudah merambat ke dada.
Di layar, Wang Sun Chien juga sedang asyik dengan Tilung.
Lebih dari dua puluh menit kami saling melumat dan meremas. Olie terengah-engah. Aku terus bernafsu. Sayangnya film dilayar sudah the end, aku juga menghentikan lumatanku, Olie merapikan baju dan rambutnya, kami kembali seperti biasa saja. Saat lampu bioskop sudah menyala terang, kami sudah lebih siap jika dilihat orang. Aku berlagak menguap, seperti orang ngantuk.
Aku puas, walaupun tidak tuntas.
Malam itu aku antarkan Olivia Fransisca, begitu nama lengkapnya . Tapi menjelang gang masuk ke rumahnya, Olie meminta aku cuma mengantarkan sampai tempat itu
"Agar kamu pulangnya gak nyasar. Kamu tinggal lurus saja sampai ke Matahari."
"Kenapa sih?"
"Gak, kakakku cerewet? Udahlah pulang sana, nanti kita ketemu lagi."
"Ok, ya, kontak aku lagi, ya?"
Tiket Bis
10 tahun yang lalu