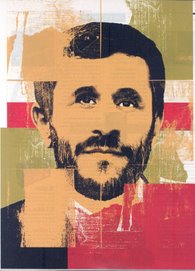Penyakit degeneratif saraf otak belum ada obatnya hingga kini. Bila sampai akut, sepanjang hidup tergantung orang lain.
***
Henry, 43 tahun, tak kuasa menahan geli. Melihat pertunjukan Srimulat di layar televisi, ia terkakak lebih keras daripada orang lain. Henry seolah-olah menyaksikan dirinya sendiri manakala seorang aktor memperlihatkan dagelan favorit Srimulat: ketidakkompakan antara keinginan dan tindakan. Tangan yang menggenggam sendok tiba-tiba bergerak ke “alamat” yang salah, dari mulut nyelonong ke mata.
“Saya jadi kayak (almarhum) Timbul. Baru akan menyuap, mulut sudah terkatup, he-he-he…,” katanya. Sudah delapan tahun Henry punya masalah dalam menyelaraskan niat atau pikiran di kepalanya dengan gerak anggota tubuhnya. Ia mengaku, akhir-akhir ini, ia sering berjalan terhuyung-huyung dan bicaranya melantur. “Jika orang enggak tahu, saya dipikir seorang pemabuk,” ujarnya seraya tertawa.
Ya, Henry, warga Kembangan, Jakarta Barat, adalah penderita spino cerebellar ataxia atau penyakit degeneratif saraf otak kecil--lebih dikenal dengan sebutan ataksia saja. “Ketika saya didiagnosis seperti itu, rasanya putus asa,” katanya.
Ataksia merupakan penyakit degeneratif yang belum ada obatnya. Dan hingga kini ilmu kedokteran modern belum dapat memperlambat gejalanya. Ataksia terjadi karena otak kecil atau cerebellum, salah satu bagian otak, mengecil volumenya, yang menyebabkan penderita akan kesulitan dalam mengontrol gerak tubuhnya. Gerakannya semakin lama semakin tak terkontrol, Dengan kata lain, perintah yang dikirimkan ke otak tidak bisa diproses dengan baik.
Seperti hemofilia (gangguan pembekuan darah) atau albino (kekurangan pigmen), gangguan fungsi otak ini antara lain disebabkan oleh faktor keturunan. “Ataksia karena keturunan umumnya diketahui pada usia 10 tahun pertama seorang anak,” ujar dokter spesialis saraf Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Abdulbar Hamid. Salah satu cara mengetes apakah seorang anak terkena gejala ataksia atau tidak adalah dengan mengetuk dengkulnya. “Jika diketuk tak ada reaksi, refleks, kemungkinan terkena ataksia,” ujarnya.
Cara lain adalah uji mata pada pasien anak. Ia disuruh menunjuk, lalu dokter atau perawat di depannya memegang boneka. Dalam jarak sekitar setengah meter itu, si anak yang matanya terfokus pada boneka disuruh berjalan mengelilingi sang boneka. Jika telunjuknya tak tepat mengenai boneka, diperkirakan ia terkena ataksia.
Ada berbagai jenis dan nama penyakit ini, dari Friedreich ataxia, athropy, sampai tipe spino cerebellar ataxia yang diberi nomor--terakhir sampai nomor 30. Ada yang berjalan limbung, ada juga yang kesulitan menggerakkan jari, tangan, lengan, dan mata. “Penderita juga akan kesulitan melafalkan kata-kata, pelo, sampai akhirnya tak bisa berbicara sama sekali,” kata dokter Abdulbar.
Masih banyak lagi tanda-tanda ataksia. Menurut alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu, penderita juga kesulitan menelan makanan dan tersedak saat minum air. “Bahkan, saat menelan, air liurnya sendiri keselek,” ujar Abdulbar. Semua gejala ini akan muncul perlahan tapi pasti; dan sesuai dengan kemampuan geraknya, si penderita harus duduk di kursi roda, dan akhirnya hanya bisa berbaring.
Selain oleh faktor keturunan, ataksia bisa disebabkan antara lain oleh tumor, gangguan metabolisme, mengkonsumsi alkohol berlebihan, kekurangan vitamin E, dan mengkonsumsi atau menghirup bahan copper (tembaga). Ataksia bisa menyerang berbagai kalangan usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. “Pada umur 60-70 tahun, ataksia biasa menyerang lewat stroke atau hipertensi,” ujar Ketua Persatuan Dokter Emergensi Indonesia itu.
Akibat-akibat yang timbul karena ataksia itu nantinya merembet ke bagian organ tubuh lain dan menimbulkan kelainan jantung (jantung membesar), gangguan pembuluh darah, otot kaku (gangguan gerak), tulang melengkung (skoliosis), keganasan infeksi pada sistem paru-paru, dan sebagainya. “Pada tingkat lain, penderita mengalami depresi dan gangguan kejiwaan lain seperti ingin bunuh diri,” kata Abdulbar.
Di Inggris, tujuh persen warga Kerajaan Uncle Jack itu terimbas penyakit ini. “Di Indonesia tak ada data yang pasti. Saya yakin banyak jika melihat gejala yang ada dalam masyarakat. Sayangnya, penderita atau keluarga penderita kurang aware terhadap penyakit itu,” kata Abdulbar, yang juga pengurus Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.
Dalam bulan kesadaran ataksia internasional, yang puncaknya jatuh pada Hari Ataksia Internasional, 25 September, sejumlah kegiatan diadakan di berbagai belahan dunia. Dari saling memberikan informasi perihal penyakit tersebut, mengadakan seminar, sampai mengorganisasi pasien untuk membantu pasien lainnya. “Seperti yang dilakukan Pepeng, yang menderita multiple sclerosis--penyakit yang menyerang sistem saraf pusat--dan mengorganisasi sesama penderita, saya berharap, begitu juga para penderita ataksia,” ujar dokter kelahiran Krukut, Jakarta, 63 tahun lalu itu.
Untuk mengobati pasien ataksia yang bukan karena faktor keturunan, dokter Abdulbar biasanya memberikan obat-obatan yang mendekati gejalanya. Misalnya, pada otot yang kaku, diberikan obat-obatan untuk melemaskan otot, atau obat-obatan untuk virus influenza A seperti amantadine. Pada gejala depresi atau masalah kejiwaan, diberikan obat seperti buspirone.
Tak mudah mendeteksi ataksia dalam tes yang dilakukan dokter saat diagnosis awal. Jika dari diagnosis diduga pasien terkena ataksia, dokter akan meminta tubuh pasien dipindai dengan magnetic resonance imaging (MRI), tes darah, dan wawancara. “Saya jelas menderita ataksia juga dari hasil MRI. Ada pengecilan pada otak bagian bawah,” ujar Henry.
Beruntung, setelah didiagnosis terkena ataksia, Henry mencari informasi dan berhubungan dengan sesama penderita di mancanegara. Ia ikut serta dalam grup Living with Ataxia. Dengan informasi yang banyak, dan tahu bahwa ia tak sendirian menderita penyakit ini, Henry merasa lebih tenang. “Ketenangan tampaknya memperlambat progres penyakit saya,” ujarnya.
(dimuat di Majalah TEMPO, edisi 24 Agustus 2009)
Tiket Bis
10 tahun yang lalu