Pukul tiga dini hari baru saja lewat, ketika Aku sampai di rumah kontrakkanku. Aku baru saja lolos dari sebuah pengalaman pahit di sebuah hotel bertaraf internasional dan sebuah kantor polisi. Tapi aku masih belum bisa menenangkan diri. Aku pergi ke kamar mandi, lalu menggambil air wudhu. Kulanjutkan dengan shalat sunnat dua rakaat. Aku harus merasa bersyukur pada Tuhan, karena sempat lolos dari suasana yang tak mengenakkan. Baju koko yang sebelumnya aku pakai ku lepaskan. Tapi celana panjang yang aku kenakan sejak pagi tak aku lepaskan.
Tidak biasanya aku tidur memakai celana panjang. Biasanya cuma kain sarung atau piyama. Istriku masih berbaring di kamar, di atas tempat tidur. Di sisinya bayi berumur sekitar 8 hari, yang baru ia lahirkan dengan susah payah. Nama anak kami yang pertama itu aku ambil dari nama orang dan julukan orang-orang suci. Sedangkan nama keduanya aku cari dalam kamus, sebuah nama indah yang artinya mata air(ku); Ali Anzi Muntazhar. Nama akhirnya pada nama Ali Anzi, Muntazhar adalah julukan Imam terakhir, sang mesiah yang ditunggu. Aqiqah dengan memotong seekor kambing jantan juga sudah aku laksanakan, bersamaan dengan sedekah berupa nasi kebuli yang dibuatkan oleh ibuku untuk para tetangga di rumah kontrakkan kami di Condet, di ujung Timur Jakarta. Rencana untuk membuat semacam upacara potong rambut di hari ke tujuh gagal, karena aku tidak menemukan seorang ustadz pun yang mau melakukannya.
Aku juga belum menemukan orang yang mau mencukur rambut bayi itu. Malah, ibuku mengancam tak mau hadir pada upacara itu bila aku memaksa untuk mencukur rambut cucunya.''Kasihan masih kecil, emak, sih, nggak tega melihat anak kecil seperti itu dicukur gundul, masih merah," kata Ibuku. Banyak anggota keluargaku juga menyarankan agar aku menunda prosesi pencukuran. Aku yang semula bersikeras hati akhirnya luluh juga, itu pun lantaran tidak berhasil menemukan seorang ustadz atau sekedar orang yang dapat memimpin upacara tersebut sesuai keyakinan agamaku.
***
Dini hari itu aku masuk ke kamar lalu menelentangkan diri di tempat tidur, di samping kiri anakku. Anakku tidur lelap di tengah kami berdua. "Yang, tidak ganti dulu dengan kain sarung," tegur istriku mesra. Kami memang sudah sepakat tidak memangggil adik atau abang, atau mama, papa. Dan juga tak sesuai ajaran agama dan adat kami yang tak boleh kawin dengan garis keturunan sedarah. Ia juga risih bila hanya memanggil namaku, walaupun aku sudah menyarankan untuk panggil nama saja.
Aku hanya diam saja tak menjawab, dan menarik nafas panjang. Jari tangan istriku ku pegang erat-erat. Kantuk mulai menyerang. Tapi pikiran dan ingatan pada kejadian yang baru saja berlalu masih membayang. Tangan istriku ku lepaskan dengan menyentak, dan aku lalu membokonginya. "Kenapa sih, yang," tanya istriku lembut. Aku diam saja. Tak berapa lama, aku mendengar suara-suara aneh, grasak-grusuk. Lalu ada seseorang yang berjalan ke arah rumahku. Ia memanggil nama yang aku tahu bukanlah namaku.
"Burhan...Burhan..," teriaknya dari luar rumah.
Aku mengintip dari balik tirai kamar. Ku lihat seorang lelaki yang menyopiri mobil sedan berwarna hitam yang membawa ku dari hotel ke kantor polisi. ''Ya, polisi itu," hatiku berkata.
Belakangan aku tahu namanya Sang Mayor. Aku menenangkan istriku. "Kamu tenang saja, ya."
Istriku diam. Ia masih tak tahu apa-apa. Aku segera bangkit dari tempat tidur, lalu mengambil kunci dan membukakan pintu. "Masuk, tapi, ssssst, anakku lagi tidur jangan berisik,'' kataku santai.
Rasa takut ku sudah kubuang jauh-jauh. Begitu pintu terbuka bukan hanya Sang Mayor yang masuk, tapi ada enam orang lainnya yang bertampang seram dan beberapa diantaranya berbadan tambun. Mata mereka liar melahap seluruh isi rumah kontrakkan ku. Beberapa diantaranya, memeriksa rumah yang hanya seluas 12 meter x 5 meter itu. Melihat muka mereka aku jadi mau buang air besar. "Sebentar aku mau berak dulu perutku mulas," kataku cuek pada Sang Mayor.
Seorang polisi bertubuh tambun yang lain malah mencegah. "Nggak usah, nggak usah berak, udah cepat ikut saja," katanya kasar.
Tapi aku tidak ambil perduli. Aku masuk ke kamar mandi dan langsung nongkrong di atas kakus. Pintu kamar mandi sempat dicegah polisi agar tidak ditutup. Dua orang menungguiku saat aku berak. Aku cuek saja, toh, perutku tak mau diajak kompromi. Aku nongkrong beberapa menit. Sial, sudah aku paksakan tai itu tak mau keluar juga. Walaupun tai tak keluar aku cebok juga. "Kok, cepat amat,"kata Sang Mayor.
"Gara-gara lu, tai gua nggak keluar,'' makiku pelan.
Aku masuk lagi ke dalam kamar ku. "Sebentar ya, aku mau pakai baju dulu," kataku pada Sang Mayor.
Aku hanya mau bicara pada dia, karena dia yang aku agak kenal dan tampak lebih simpatik dibandingkan yang lain. "Udah, nggak usah apa adanya saja,"kata polisi yang lain, berusaha mencegah.
Aku cuek saja dan mengambil baju dari lemari. Pintu kamar ditahan polisi agar tetap terbuka. Sang Mayor berdiri di depan pintu kamar memperhatikan gerak-gerikku. Sambil aku mengenakan pakaian, aku masih sempat memberitahukan secara sekilas pada istriku. "Aku pergi sebentar ya, aku tadi sudah berada di kantor polisi, lalu aku pulang dulu. Kamu tenang saja, deh, tenang, ya!'' kataku.
Istriku diam saja, tertegun tampaknya.
Lalu polisi bertubuh tambun itu mengambil secarik kertas berwarna merah. "Kami dari polisi,'' kata polisi itu pada istriku sekilas.
Digiring oleh enam orang polisi, aku keluar dari rumah menembus kegelapan dini hari di sebuah perkampungan di kawasan Condet. Dari kejauhan kulihat bapak ketua RT masuk ke sebuah gang kecil menuju rumahnya. Rupanya tugasnya sebagai kepala kampung sudah dipenuhi, memberitahu kepada polisi rumah salah seorang warganya untuk ditangkap. Aku dan para polisi berjalan kaki sejauh 300 meter, menyusuri jalan kampung.
***
Kampung kami itu selalu di tutup portal mulai tengah malam, hingga subuh. Jadinya, mobil Toyota kijang polisi hanya bisa parkir di ujung gang, tepatnya di Jalan Raya Condet. Lalu aku dipaksa masuk ke mobil kijang. Sebuah mobil Suzuki Carry tampak membayangi mobil yang membawaku. Tampak wajah riang, wajah kemenangan di air muka polisi-polisi. Meluncurlah cerita tentang kesuksesan dalam proses penangkapan ku. "Saya yakin ia bakal pulang ke rumah, sebab bukan kriminal sih,'' kata Sang Mayor membuka percakapan pada kawannya. Suara Handy Talky terus terdengar.
Cerita penangkapan dilaporkan lewat; "Kijang sudah di tangan," lapor Sang Kapten. Toyota Kijang itu dipacu kencang-kencang menuju kantor polisi. Sampai di sana, seseorang yang berpakaian preman, bermuka sedikit kumal, berusaha memukulku. ''Oh, ini yang kabur, bikin susah aja luh,'' sambil tangannya berusaha mau memukul.
Aku menghindar. Tak kena. Ia juga tak meneruskan pukulan, walau polisi yang menggiringku tak mencegah. Aku dibawa dan ditemukan kepada seorang lelaki berkumis dan bertubuh tambun, berpangkat Mayor. Haji Abdullah namanya. Polisi lain biasanya memanggil Haji Mayor. Ia kepala seksi reserse. Tak lama kemudian, aku dibawa menghadap atasannya, Sang Kepala, Kolonel Nurfaizi. Pria berpakaian putih itu tampak berusaha untuk menjaga wibawa, walau ia tampak baru saja terpaksa bangun tidur. Wajahnya masih kuyu.
Ia langsung bertanya-tanya seadanya, dan menuduh aku kabur dari kantor polisi tanpa izin. Aku menyangkal. "Saya ijin ke piket. Lagipula, memangnya saya ditangkap?"
"Ijin, ijin siapa, ayo tunjukkan orangnya," ujar Sang Kepala mendesak. "Ya, ijin polisi yang ada dipiket,'' jawabku lagi.
"Haji Mayor, coba antarkan ke piket, suruh tunjuk siapa orangnya yang mengijinkan dia dari kantor ini," perintah Sang Kepala pada Haji Mayor.
Aku dibawa oleh Haji Mayor, ke ruang piket. "Ayo, tunjukkan yang mana orangnya," desaknya. Aku melihat- lihat. "Ayo, yang mana?" desaknya lagi.
"Wah, nggak ada, tapi kalau lihat label namanya saya ingat," ujar ku santai. Aku tahu ada orangnya di ruang jaga itu, tapi tidak tega mengorbankan orang kecil hanya karena sekedar ingin bebas atau menyenangkan atasannya.
Akupun kembali dibawa ke ruang Sang Kepala. "Bagaimana, ada orangnya?" tanya Sang Kepala. "Nggak ada, pak, katanya," sambut Haji Mayor cepat.
Lalu keluar lagi seorang polisi, yang sempat membawakan teh waktu aku disekap di ruang data Sang Kepala tadi malam. "Ini orangnya bukan," kata Sang Kepala lagi sambil menyelidik. "Oh, bukan, saya nggak kenal orang ini," kata ku berbohong. Aku yakin berbohong seperti ini dibenarkan Tuhan.
Polisi kelas bawah ini bukan termasuk orang-orang yang berbuat zalim untuk kepentingan dirinya. Para atasannya yang tanpa segan-segan mengorbankan bawahannya untuk kenaikan pangkat. Aku yakin itu. Waktu masih jadi wartawan di Bandung aku sering bertugas di kepolisian. Padahal sesungguhnya aku kenal polisi yang baik itu, tapi aku diam saja.
Ia kelihatan gemas melihatku, karena kabarnya ia sempat diperiksa provoost gara-gara aku menghilang dari kantor polisi. "Kenapa kamu kabur?" tanya Sang Kepala lagi.
"Saya merasa tersinggung dibawa kesini, lalu didiamkan di sebuah ruangan selama tiga jam, tanpa ditanyai, ataupun diberitahu akan diapakan," sambungku lagi.
Lalu Sang Kepala meminta Haji Mayor menulis segala keterangan yang aku berikan.
Ia tanya lagi soal buletin Independen yang kami terbitkan. Ia menekankan soal penerbitan tanpa izin. "Ini penerbitan tanpa SIUPP, kamu yang menerbitkan, ya?" desak Sang Kepala.
"Bukan," jawabku singkat.
"Ah, bohong. Di buletin itu ada nomor rekening atas nama kamu,'' kata Sang Kepala, langsung menuduh dan mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya nomor rekening atas namaku berarti aku penanggung jawab atas buletin itu.
"Pokoknya kamu orang yang bertanggung jawab. Kan, ada nama kamu disitu!" putus Sang Kepala, sok kuasa.
Aku hanya tertawa getir. "Susah berbicara sama orang yang merasa berkuasa. Apa mau dikata. Pokoknya ia sudah bilang, berarti kekuasaannya yang berbicara dan bukan lagi soal hukum atau aturan yang ada, presumtion of innoncence. "Semau kamulah!" makiku.
"Ah, dasar wartawan!"sergah Sang Kepala terperangah atas jawabanku. Aku jadi ingat lagu Rhoma Irama, kunyanyikan keras-keras di hadapan Sang Kepala, "hei...jangan mentangg-mentang kuasa...lalu seenaknya..." Lagu dangdut yang pas rupanya.
***
Aku lalu dibawa kembali ke ruang Haji Mayor. Lalu minta ijin untuk sholat subuh. Aku ingin sedikit bersopan-sopan minta ijin, tapi rupanya dianggap sebagai ketertundukan. Polisi yang lain melarang. "Nggak usah, nggak usah sholat,'' cegahnya.
"Eee, enak aje, melarang orang sholat, ini melanggar HAM, tahu!" kataku. "Tuh, lihat matahari sudah mulai nongol dari ufuk timur. Masak bodoh, aku mau sholat. Ayo, mana kamar mandi tunjukkan?" mulutku nyerocos sendiri tak terkendali.
Sambil ditunggui polisi lainnya. Aku kencing, dan berwudhu. Lalu shalat di ruang Haji Mayor. Setelah shalat dua rakaat, aku mengantuk dan tak enak badan, jadi tidur di bangku panjang. "Badan saya lemas, pak, saya mau tidur dulu,'' kataku pada Haji Mayor.
"Jangan, mau ditanya dulu," ujar Haji Mayor berusaha mencegah.
"Ah, saya ngantuk, percuma saja," kataku tak perduli dan tidur di bangku panjang.
Setelah bangun aku terus diperiksa hingga hampir tengah malam. Sebuah pemeriksaan yang melelahkan. Dan polisi penyidik yang terlihat bodoh terus mengulang-ngulang pertanyaan. Tampaknya memang sudah jadi kebiasaan mereka untuk menggunakan kekerasan dalam mendapatkan keterangan. Tapi menghadapi aku mereka sepertinya tak berani melakukan kekerasan.
***
Setengah jam menjelang tengah malam aku dibawa ke ruang bawah tanah, ke ruang tahanan kantor polisi. Jaket, sepatu, baju dan celana disuruh lepas dan aku serahkan pada polisi penjaga ruang tahanan. Dompetku juga diambil dan dibuka-buka isinya. Ada empat lembar dua puluh ribu perak dan tiga seribuan. Dua orang polisi berpangkat Sersan memaksa aku membuka celana panjang, karena dalam tahanan tak boleh pakai celana panjang. "Takut digunakan buat bunuh diri, pernah ada kejadian," ujar polisi itu menakuti-nakuti.
Aku disuruh memakai celana pendek bekas yang terongggok di sudut ruang periksa tahanan. "Nggak mau, nanti budukan," kataku tegas.
"Ya, sudah, pokoknya, kamu harus pakai celana pendek. Nih silet, jangan buat motong urat nadi, ya,"kata polisi itu lagi. Silet yang tinggal sepotong itu diberikan padaku. Dan aku memotong celana panjangku menjadi celana pendek sedikit di bawah lutut. Sang Sersan kembali menakut-nakuti aku soal tahanan yang dicampur dengan tahanan lain dan akan terjadi 'sesuatu' yang menyeramkan. "Nah, ini duit, kami simpan dulu ya. Di dalam sel, nggak boleh bawa duit. Nanti kamu di kompas," ujar polisi itu.
Seumur-umur belum pernah aku masuk penjara sebagai penghuni, walau berulang kali mengunjungi penjara untuk wawancara. Aku sempat berunding untuk mendapat tempat yang lebih baik, agar tak dicampur dengan tahanan lain. "Boleh, asal kamu memberi mereka uang. Untuk keamanan," sambut polisi cepat.
Nyatanya janji itu tak pernah dipenuhi tapi uangnya sudah mereka terima. Aku tetap digiring ke kamar penampungan. "Kamu disini dulu. Tempat lain penuh," kata polisi yang tadi menerima uangku.
Perasaan seram menyelimutiku ketika memasuki lorong gelap melalui jeruji-jeruji besi, sel-sel penjara. Aku membayangkan seperti di film-film ada ratusan tahanan berteriak-teriak dan seolah-olah mau memakan kami. Seperti Dr. Hanibal Lecter di Silence of The Lamb. Tapi ternyata bukan seperti itu.
Tepat di pojok ruang A-13 yang gelap dan bau pesing aku dimasukkan. Di sana sudah ada 18 tahanan lain yang tergeletak tak beraturan di lantai berlantai tripleks tipis. Beberapa diantaranya bermuka lebam, matanya biru, dan ada juga yang hanya pakai celana dalam saja. Oman namanya. Aku langsung menyalami semua penghuni sel A-13 sebelum berjalan ke ujung tripleks. "Permisi, ya, aku ngantuk, tidur duluan," kataku mengambil tempat di pojok.
Kulihat para tahanan itu tidur di atas tripleks berdesak-desakan bercampur baur pasal kejahatannya dan juga baunya. "Ya, disini aja, disitu bau pesing,'' kata seorang penghuni yang belakangan aku dengar preman pembunuh asal Pasar Minggu. Aku akhirnya ikut tidur di atas triplek bersama pembunuh, pencuri, pemabuk, penipu, pengedar narkotika dan pelaku kriminal lainnya, yang aku pikir ternyata punya sesuatu yang lebih mulia dibanding para polisi.
Polisi yang sudah menerima uang dengan janji menempatkanku ke tempat yang lebih baik, cuma bilang. "Hei, titip ini, ya?" katanya langsung pergi. Suara Handy Talky yang dibawanya berbunyi: "kreek...kreek...kijang sudah di kandang?".
"Huh, dasar tikus!" maki Oman.
"Siapa, yang bilang itu!" teriak polisi berbalik ke sel.
"Gue, mau apa lu?" tantang Oman dengan mata melotot. Polisi itu diam saja, meloyor pergi.
Rutan Salemba 17 Desember 1995
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















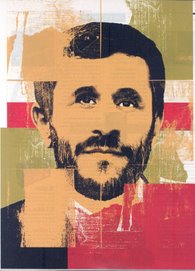









Tidak ada komentar:
Posting Komentar