Menjelajahi Islam di Barbes dan Belleville
Seorang lelaki berjanggut dengan celana nantung di atas mata kaki, berkopiah putih dengan balutan baju dingin abu-abu melepaskan sepatu memasuki pintu kecil berwarna hijau tua. Di dalamnya tampak tiga orang serupa berada di gang sempit menuju pintu utamanya. Bangunan itu hanya sebuah ruang selebar 6x6 meter di pojok jalan Jean.P.Timbaut, Belleville, Ibukota Perancis, Paris. Di luar tampak sebuah tulisan berbahasa Arab, dalam bahasa latin dibaca Masjid Umar Ibn Khattab.
Masjid atau tepatnya bila disebut musala itu pada 21 Desember
2002, dilaporkan ada kekerasan berdarah. Ketika itu sekelompok salafi merampas uang zakat dan mengancam Imam masjid tersebut, Imam Hammami. “Ada orang dibunuh di dalam masjid oleh seorang fundamentalis,”kata Fredo Rochechart, penduduk setempat.
Polisi akhirnya menangkap dua orang dari pelaku kekerasan berdarah itu ; Karim Bourti, anggota the Algerian Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), dan kaki tangannya, seorang mualaf bernama Rudy Terranova. Polisi Paris sampai kini terus mengawasi masjid yang berorietasi ke kelompok salafi itu. Masjid salafi tersebut seringkali mengundang ulama-ulama asal Saudi Arabia untuk mengajar dan menguji calon mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Mekkah atau di Universitas Madinah.
Masjid Umar bin Khattab, hanyalah sudut kecil di Paris, yang dikuasai kaum salafi. Konon, salah seorang pelaku pengeboman 11 September di New York, Amerika Serikat, Zacarias Mousaiu, juga pernah mondok di rumah “tuhan” itu. “Benar, kebanyakan kaum fundamentalis itu Wahabi, tapi itu hanya sekelompok kecil, dan bukan mayoritas penganut Islam di Perancis,”ujar Imam Masjid Paris, Doktor Dalliel Boubaker.
Belleville, tampak tak berbeda dengan tempat lain di Paris. Jalan-jalannya pas ukuran mobil sedan, turun naik. Tempatnya cukup bersih dan tenang. Ada beberapa toko yang menjual buku-buku Islam, baju dan perlengkapan muslim. Toko buku Tawhid tak jauh dari musala Umar tampak sebuah notebook untuk anak-anak dengan huruf Arab terpampang ke luar dari kaca etalasenya.
Belleville sebenarnya bukan hanya kawasan muslim, pada awalnya daerah campuran, tempat tinggal kaum imigran Yahudi, Cina, Islam dan orang Paris asli atau Gallic Parisii. Saat Tempo menyusuri daerah itu, Hari Sabtu, beberapa toko milik Yahudi tutup. Padahal pada saat itu toko-toko lain justru buka meraup pembeli. Belakangan kaum Yahudi semakin sedikit, tapi orang Islam dari Tunisia semakin menguasai daeah tersebut.
Di sudut yang sepi, sebuah tempat minum teh “Salon The Tea” tanpa nama, tampak buka dengan lampu yang tak begitu terang. Sesekali terdengar suara teriakan dalam Bahasa Arab dan bunyi suara siaran sepakbola dari televisi. Suara itu mengundangku untuk mampir. Maksudnya sekedar minum teh.
Begitu masuk benar saja, dua kelompok laki-laki berwajah timur tengah asyik bermain kartu remi. Sesekali matanya melihat tayangan sepak bola di dua televisi ukuran 39 inchi yang terpampang di atas dinding. Mulut mereka juga tak berhenti, berteriak mengomentari sepakbola atau kartu yang mereka pegang. Beberapa orang diantara juga asyik menyedot sisha. Waktu baru pukul lima sore, tapi gelap sudah menggayuti langit-langit Paris di musim dingin.
Tampak tabung-tabung untuk mengisap shisha teronggok di bawah layar televisi. Tempo memesan shisha rasa apel, dan sepoci teh dengan daun mint, khas Tunisia. Di tempat minum teh itu tak ada minuman beralkohol. Beberapa perempuan berjilbab juga tampak lalu lalang di depannya, acuh saja. “Kami senang tinggal di Paris, yang penting saling menghormati perbedaan,”kata Loutfi, 39 tahun, imigran asal Magrib, Tunisia.
Menurut ayah dari dua anak yang sudah tinggal 20 tahun di Belleville, tak punya masalah dengan kehidupan ala Perancis. “Di daerah tempat tinggal saya ini, ada masjid, bar bahkan sexshops, ya, biasa saja, tergantung pilihan orangnya,”ujar Loutfi. Anak-anaknya juga sekolah di sekolah Perancis. “Isteri saya orang Paris juga asal Tunisia. Kuncinya hidup disini toleransi,”kata Loutfi.
Belleville pada bulan Ramadhan, menurut Loutfi, tampak berbeda. Sepanjang jalan penuh dengan gerai penjual kurma, buah zaitun, madu. kacang almond, pistachio dan berbagai penganan ala timur tengah. Ali Boudine imigran asal Tunisia mengubah restorannya menjadi toko roti selama bulan puasa. “Pada bulan suci semua orang bergembira. Saya punya pelanggan Yahudi, Katolik dan Muslim, mereka kesini membeli kue-kue. Kami hidup bersama, menentang perang, kami hidup di Perancis dan kami semua sama,”katanya.
Sepakat dengan Ali, Arlette, perempuan Yahudi asal Tunisia, juga senang dengan suasana di Belleville. “Di distrik ini kami semua bersaudara, orang Perancis asli, Yahudi atau Arab,”ujar wanita yang datang ke Paris sejak 40 tahun silam.
Hanya dua stasiun kereta metro, tak jauh dari kawasan lampu merah Paris, Picadilly, ke arah bukit makam mountmarte, daerah tertinggi di Paris, 130 meter di atas laut, ada kantung muslim lainnya, Barbes.
Barbes-Rochechouart, begitu nama stasiun metro-nya dilewati line 2 dan 4. Barbes berasal dari nama Armand Barbes yang tewas dalam kebakaran besar akibat perang pada 10 Agustus 1903, di daerah tersebut. Juga pada 1941, Kolonel Pierre-Georges Fabien tewas ditembak tentara Jerman di tempat itu.
Berbeda dengan Belleville yang tenang dan sepi, Barbes, yang termasuk arroundisement atau ring 18 lebih ramai, hiruk pikuk dan agak jorok. Delapan puluh persen penduduk daerah itu imigran asal Aljazair dan negara Afrika lainnya. Tak heran jika tampak lelaki dan perempuan berwajah Negro lalu lalang di kawasan tersebut. Ayah pemain sepak bola Zinedine Zidane pertama ke Paris tinggal di Barbes ini, sebelum pindah ke Marseille pada 1960-an.
Di pasar Barbes, persis, seperti kaki lima Pasar Mesteer, Jatinegara. Lapak-lapak jualan ikan, kain dan barang-barang elektronik bercampur baur. Beberapa diantaranya menggelar dagangan di atas kap mobil sedan mereka. Lelaki-lelaki yang menenteng jam tangan dan dompet Louis Vutton palsu seharga 10 Euro ditawarkan kepada para pejalan kaki yang lewat. Warna Afrika lebih kental di daerah ini. Toko-toko menjual kaset dan CD Afrika juga bertebaran. Bahkan Barbes pernah punya kelompok musik Orchestre National de Barbes, dan menelurkan sebuah album CD, Poulina. “Dulu aku suka menonton pertunjukkannya, sekarang entah kemana tak pernah muncul lagi,”kata Fredo.
Perancis memang “rumah” orang-orang muslim di Eropa, sekitar sekitar enam juta muslim tinggal disini. Sebagian besar tinggal tinggal di Paris. Tak salah jika Menteri Dalam Negeri Nicolas Sarkozy mengajak umat Islam yang tinggal di Prancis terlibat dalam proses demokrasi dan menjauhkan diri dari pandangan ekstremis.
Menguatnya aksi kekerasan dan terorisme belakangan ini, setelah peristiwa 11 September 2001, memang menimbulkan ketakutan orang-orang Eropa terhadap Islam. Lalu orang menengok ke Prancis, yang paling banyak “menampung” orang-orang Islam dari negara-negara bekas jajahannya.
Beruntung Pancis punya Laicite, sistem sekular, yang memisahkan agama (yang saat itu diwakili gereja) dengan pemerintah sejak 1905. Dengan laicite, kebebasan beragama dijamin setara. Untuk mengantisipasi konflik, pemeluk agama apa pun dilarang memakai simbol agama, seperti kalung salib, topi Yahudi atau kerudung di sekolah-sekolah, rumah sakit atau kantor-kantor pemerintah. Namun, pemerintah tak melarang para pemeluk agama beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing bahkan menjaminnya selama berada di wilayah pribadi masing-masing.
Seperti kehidupan yang terjadi di Belleville dan Barbes. Bahkan saat Tempo berada di Belleville sekelompok perempuan berjilbab berunjuk rasa dengan warga Prancis lainnya, menentang upah buruh murah yang dibayarkan pengelola gerai fesyen Tati. “Kami menuntut hak yang sama, tak ada perbedaan bila bergaul dengan warga Prancis lainnya. Agama kami berada di dalam hati,”ujar Sekinah, salah seorang perempuan yang ikut demo sore itu.
Hampir serupa dengan pernyataan Presiden Dewan Peribadatan Muslim Prancis, Dalie Boubaker,"Islam bukan alat meraih kekuasaan dan bukan identitas politik, tetapi cara menjalani kehidupan."
Desember 2006
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















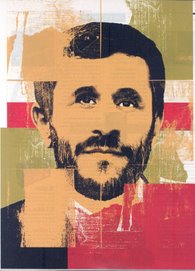









Tidak ada komentar:
Posting Komentar