RUU KUHP, yang sudah 20 tahun digarap, dituntut untuk menampung syariat Islam. Bisakah hukum di daerah berbeda dengan hukum nasional?
SEBENTAR lagi Indonesia akan punya hukum pidana buatan sendiri. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan parlemen Belanda pada akhir abad ke-19, yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918, tinggal sejarah. Rancangan undang-undang (RUU) pengganti KUHP segera dirampungkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Rencananya, RUU itu akan disampaikan ke Presiden pada akhir Januari 2002, untuk kemudian diajukan ke DPR.
Namun, calon hukum pidana nasional ciptaan dalam negeri itu punya ganjalan serius. Kini RUU KUHP, yang sudah memuat ratusan pasal pidana, dituntut pula untuk mencantumkan syariat (hukum) Islam, dalam hal ini pidana Islam--menggunakan istilah pidana pada hukum Barat. Tentu hal ini amat mengentak. Bagaimana mungkin hukum pidana yang berlaku untuk semua warga Indonesia dan di wilayah Indonesia akan memuat hukum pidana khusus bagi kalangan Islam?
Selama ini, sejak Indonesia merdeka, praktis pidana Islam tak diberlakukan. Sedangkan hukum perdata Islam--juga dengan terminologi perdata hukum Barat--tetap dilaksanakan melalui pengadilan agama. Perkara perdata Islam menyangkut perkawinan (termasuk perceraian), waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Tak aneh, bila pidana Islam diberlakukan, orang pun membayangkan hukuman yang menyeramkan, seperti rajam bagi pelaku perzinaan dan potong tangan terhadap pencuri.
Secara formal, baru Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menuntut pemberlakuan pidana Islam. Hal itu bisa dimengerti lantaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh telah memberikan keleluasaan bagi daerah Serambi Mekah itu untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk menerapkan syariat Islam. Di Aceh, kabarnya, sedang disiapkan peraturan daerah yang disebut Qanun untuk mengatur syariat Islam.
Namun, selain di Aceh, ternyata tuntutan syariat Islam bergema di Provinsi Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Cianjur dan Garut di Jawa Barat. Memang, tuntutan di ketiga daerah ini belum dituangkan lewat undang-undang, tapi baru secara politis, antara lain lewat gelombang demonstrasi ke DPRD.
Tak terbayangkan bila daerah lain menuntut hal serupa. Padahal, secara teoretis, kalau urusan hukum (dan peradilan) serta keuangan, keamanan, dan luar negeri ditangani langsung oleh daerah, itu mirip ciri-ciri negara federal.
Salah seorang anggota tim penyusun RUU KUHP, Andi Hamzah, mengaku tak sependapat bila hukum pidana suatu daerah berbeda dengan hukum nasional. Sekadar persoalan kecil yang bisa terjadi: bagaimana bila orang yang dituduh melakukan delik di daerah itu berasal dari daerah lain? “Hukum pidana tak bisa diotonomikan. Harus ada unifikasi, satu hukum pidana untuk seluruh Indonesia,” kata Andi Hamzah.
Kalaupun mau dicari perbandingannya, Andi menambahkan, itu seperti yang diterapkan Cina, dengan membolehkan daerah otonom menambah beberapa pasal untuk tindak pidana tertentu. “Itu pun harus disetujui dulu oleh DPR pusat,” ujarnya. Bisa pula daerah melengkapinya dengan pidana tambahan, misalnya denda. Contohnya adalah hukuman khusus di Bali bagi pelaku yang menyetubuhi hewan. Bali boleh menerbitkan peraturan daerah bersanksi denda untuk delik tersebut.
Lain lagi pendapat koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Firmansyah Arifin. Menurut Firmansyah, sebaiknya syariat Islam jangan ditilik dari aturan materiil berupa pasal-pasal dan ancaman hukumannya, tapi dikaji dari sisi spiritnya, seperti asas keadilan, persamaan hukum, dan toleransi. “Kalau pemahaman spirit syariat Islam yang dikedepankan, tentu tak mengkhawatirkan,” ujar Firmansyah.
Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Aceh, M. Nasir Jamil, menyatakan bahwa Qanun belum disiapkan untuk mengatur hukum pidana Islam seperti potong tangan dan rajam. “Aceh masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, hukumnya akan disesuaikan dengan KUHP nasional,” ujar Nasir.
Kontan pernyataan Nasir ditentang oleh salah seorang anggota tim penyusun Qanun Aceh, Al Yasa Abu Bakar. Kata Al Yasa, tak ada masalah bila hukum pidana di Aceh berbeda dengan KUHP nasional. “Kalau KUHP bisa menampung aspirasi masyarakat Islam, kami akan merujuknya. Kalau tidak, hukum yang berlaku di sini yang digunakan, sesuai dengan wewenang otonomi khusus Aceh,” ujar ahli hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Aceh itu.
Dengan catatan, kata Al Yasa, syariat Islam hanya berlaku bagi pemeluk Islam. Bagi nonmuslim tetap berlaku hukum pidana nasional. Bagaimana bila terjadi benturan antara syariat Islam dan KUHP?
Agaknya, tuntutan pemberlakuan syariat Islam, menurut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Abdul Gani Abdullah, akan diakomodasi dalam RUU KUHP. Alasannya, RUU KUHP yang sudah digarap sejak 20 tahun lalu itu belum mengantisipasi perubahan politik yang terjadi secara drastis setelah Orde Baru tumbang, termasuk perkembangan otonomi khusus Aceh dan pemberlakuan syariat Islam. Lagi pula, “Urusan perdata Islam dan pengadilan agamanya kan sudah jalan. Tinggal sekarang pidana Islamnya,” kata Abdul Gani.
Adapun soal posisi syariat Islam, menurut Abdul Gani, itu akan menjadi semacam aturan khusus (lex specialis) terhadap KUHP, yang merupakan aturan umum (lex generalis). Aturan khusus dimaksud tak lain Qanun di Aceh ataupun Perbasus di Papua. “Daerah tetap menjalankan KUHP nasional, bersamaan dengan hukum khusus mereka. Kalau aturan khusus sudah diakomodasi dalam KUHP, tentu tak perlu lagi ada penamaan syariat Islam,” kata Abdul Gani, yang juga guru besar hukum Islam di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
Ahmad Taufik, Darmawan Sepriyossa (Jakarta), Zainal Bakri (Lhokseumawe)
---ini tulisan 6 tahun yang lalu, dimuat Majalah Tempo, 14 Januari 2002--
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















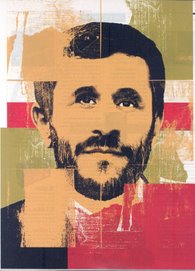









Tidak ada komentar:
Posting Komentar