Industri kreatif di beberapa daerah berkembang dengan jalannya masing-masing. Mengutamakan ciri khas setempat.
Lupakan Bandung. Industri kreatif di sana sudah karatan. Banyak kota lain di Indonesia punya kisah tak kalah menarik dibanding ibu kota Priangan itu. Ada fashion jalanan nun di Jember, juga industri kreatif yang tumbuh berdampingan dengan warisan kultural di Yogyakarta, atau Bali yang tak pernah berhenti berkreasi. Mereka berusaha tumbuh dan membesar dengan caranya masing-masing.
Jember
Fashion Jalanan
Jalan protokol di Kota Jember sepanjang 3,6 kilometer disulap menjadi catwalk. Peragawati dan peragawan memamerkan beragam busana yang terbuat dari bermacam bahan, termasuk dedaunan dan bulu-bulu. Mereka tampil berani dan atraktif. Para peraga itu tidak harus cantik dan tampan atau bertubuh langsing dan tegap. Mereka boleh pendek, gendut, dan memiliki ukuran tubuh apa adanya. Sekitar 200 ribu penonton tumplek blek memadati arena pertunjukan.
Itulah keramaian Jember Fashion Carnaval (JFC), yang digagas Dynand Fariz. Kemeriahan yang berlangsung pada awal Agustus lalu itu merupakan yang ketujuh kalinya. Meski Dynand mengaku tak menghitung pendapatan dari acara yang makin ramai tersebut, berkat karnaval busana itu, dia jadi pesohor. Dynand beberapa kali diundang ke Jakarta, sebagai salah satu wakil penggerak industri kreatif di daerah. Pria 45 tahun itu bahkan diberi kesempatan mempromosikan Jember Fashion Carnaval ke India dan Inggris.
Awalnya, ide Dynand tak lebih sebagai bahan tertawaan. Bagaimana mungkin memperkenalkan kota berpenduduk dua juta jiwa lebih di Jawa Timur yang dikenal sebagai “kota santri” itu dengan karnaval ala Rio de Janeiro, Brasil. "JFC ditanggapi negatif. Dianggap mimpi di siang bolong. Bertolak belakang dengan tradisi, budaya, religi masyarakat," kata Dynand.
Dasar Dynand ndableg, dia dan kawan-kawannya sesama alumnus Jurusan Seni Rupa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya jalan terus. Dynand mencoba meyakinkan banyak pihak bahwa dunia mode dan fashion bukan monopoli kelas atas yang diperagakan di mal atau hotel berbintang. “Bisa dilakukan masyarakat bawah, di catwalk terbuka, seperti jalan raya,” kata Dynand. Bahan-bahannya pun bisa dibikin dari kain bekas, botol plastik, atau kulit, daun, dan akar tanaman. Semuanya dibikin secara kreatif-eksperimental.
Motivasinya satu: prihatin atas perkembangan daerahnya; banyak anak muda yang tak mampu melanjutkan sekolah dan tak memiliki masa depan jelas. "Saya bertekad membuat sesuatu yang melibatkan mereka dan menjadi kebanggaan diri dan masyarakat Jember."
Awalnya, Dynand memulai karnaval fashion dengan 45 orang berkeliling kampung dan alun-alun Jember pada 2002. Makin tahun pesertanya makin ramai dan meriah. Hingga pada 2007, ketika ada “Bulan Berkunjung ke Jember”, karnaval fashion menjadi salah satu acaranya. Dynand bercita-cita Jember menjadi kota wisata mode pertama di Indonesia.
Yogyakarta
Desain Lokal Kaya Sindiran
Kota gudeg ini sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri kreatif, terutama kerajinan. Tapi budaya urban pun tak kalah punya pengaruh di kota yang masih punya “raja” ini. Dagadu, misalnya, sebuah bisnis kaus berbasis kata-kata lucu. Karena laku, bisnis ini kemudian diproduksi besar-besaran dan banyak ditiru. Bukan hanya batik dan kerajinan tradisional, Dagadu pun sudah menjadi salah satu identitas Yogyakarta.
Selain Dagadu, masih banyak industri kreatif yang menyerap budaya urban. Misalnya di ujung gang di Jalan Kaliurang Kilometer 7,8, Kabupaten Sleman. Di sana ada sebuah rumah mungil yang memproduksi beraneka desain grafis. Produknya dijual sampai ke Singapura. Indieguerillas, begitulah si pendiri--pasangan suami-istri Miko Bawono dan Santi Ariestyowanti--menamakan bisnisnya.
Mereka terilhami oleh cara gerilya tokoh revolusioner dari Amerika Latin, Che Guevara. “Model kerja kami pada awalnya kan bergerilya juga, dengan membaca buku, bahkan bolak-balik ke Jakarta, untuk melihat-lihat model desain. Sebab, waktu itu Internet belum masuk. Di Yogyakarta pun, buku soal desain grafis terbatas,” kata Santi.
Desain cover album milik grup musik Sheila on 7, Kisah Klasik, pada 1999, adalah bisnis pertama yang mampir. Karena grup band-nya terkenal, tawaran pun berdatangan. Tapi mereka menolak ketika diajak boyong ke Jakarta. Kenapa? Ya, karena mereka sudah punya komunitas di Yogyakarta--mereka punya bahasa dan guyonan yang sama serta tempat nongkrong seselera pula.
Tidak hanya menolak pindah ke Ibu Kota, gaya desain pun tak mau meniru tren yang ada di Jakarta. Desain Indieguerillas mencampurkan budaya lokal dan selera muda. Misalnya menggunakan tokoh Bagong yang mengenakan pakaian penyanyi rap. “Ada kesan lucu, ada sindiran,” kata Santi.
Modal? Jelas masih jadi masalah. Pada 2002, misalnya, dari hasil kumpul-kumpul dengan teman-teman, mereka menerbitkan majalah dua bulanan, Outmages, tapi macet karena kurang modal.
Toh, dengan semangat “kekeluargaan”, Indieguerillas tetap hidup, bahkan berkembang. Tak jarang, sekali pesanan bernilai puluhan juta rupiah. “Jika ada order, kami juga membaginya ke teman-teman. Kami yang menangani desain, teman percetakannya, fotografernya, dan sebagainya. Kolektiflah,” kata Santi. “Jadi, prinsipnya, kerja sambil menghidupi teman,” ujarnya.
Denpasar
Desa Masuk Kota
Desa Kertalangu terletak di Kota Denpasar, tepatnya di tepi Jalan Bypass Ngurah Rai. Lanskap seluas 80 hektare itu bukan desa “kesasar” masuk kota, tapi sengaja dibuat agar ciri pedesaan Bali--lengkap dengan sawah hijaunya--bisa hadir di kota itu.
Dan seperti layaknya Bali yang sudah banyak dikenal orang sebagai daerah wisata eksotis dan natural, Desa Kertalangu “didesain” sesuai dengan kriteria itu. Menurut penggagasnya, Dewa Gede Ngurah Rai, 43 tahun, kawasan yang mulai dibuka pada Juni 2007 itu berusaha mengawinkan upaya pelestarian pertanian, seni budaya, dan usaha kerajinan.
Di sana tersedia berbagai fasilitas, dari jogging track, pemancingan, pijat dan spa, restoran, panggung kesenian, sampai pasar seni. Masih ada kursus kilat membatik, membuat keramik, lilin, atau kerajinan gelas, dan aktivitas lain. Untuk sekadar menyusuri jogging track, pengunjung tidak dikenai bayaran. Tapi, jika mau ikut berbagai kursus, turis lokal harus membayar Rp 20 ribu, sedangkan turis asing US$ 7 atau hampir Rp 70 ribu.
Lahan yang digunakan merupakan milik para petani Desa Kesiman Kertalangu. Mereka sepakat tak menjual tanahnya dan bertahan sebagai petani. Mereka pun tetap mengerjakan sawah dan mengambil hasilnya. Tentu saja dengan tambahan kreativitas, yaitu menguji coba bibit unggul dan menerapkan pertanian organik.
Dewa Rai juga membangun fasilitas di atas lahan seluas tiga hektare agar lahan pertanian layak menjadi obyek wisata. “Kalau pertanian hilang, budaya Bali juga akan hilang. Kami tidak mau mengalami nasib seperti warga Betawi di Jakarta,” ujarnya.
Desa Kertalangu juga menjadi sebuah komunitas. Tenaga yang bekerja di berbagai fasilitas berasal dari desa itu, termasuk penari dan penabuh gamelan yang menghibur tetamu. Turis dapat mempelajari aneka kerajinan, menikmati suasana persawahan, dan menonton pertunjukan seni tradisional Bali. Pokoknya, Bali banget….
Ahmad Taufik, Mahbub Djunaidy (Jember), Rofiqi Hasan (Denpasar), Pito Agustin Rudiana (Yogyakarta)
(dimuat di Majalah Tempo 22-28 Sept 2008)
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















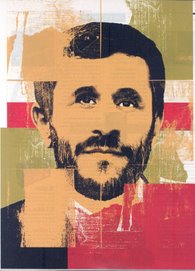









Tidak ada komentar:
Posting Komentar