Kota Tua Jakarta memang masih kumuh, rawan, dan belum tertata. Tapi banyak yang mengais rezeki dari sektor informal di sini.
**-
PEDAGANG buah dari Bogor dan Bojong Gede sibuk menurunkan keranjang-keranjang yang masih tertutup daun pisang. Begitu juga beberapa pedagang kaus dan sepatu menurunkan bergelondong-gelondong barang jualan mereka. Para kuli panggul asal kulon--begitu sebutan kuli asal Banten--pun tak kalah sibuk berebut mengangkut berbagai barang yang baru turun dari kereta listrik jurusan Bogor-Stasiun Kota. Kesibukan sudah amat riuh di stasiun kereta api Beos ketika sinar matahari baru nongol dari ufuk timur.
Mungkin itulah karakter stasiun Beos, singkatan dari Bataviasche Ooster Spoorweg (BeOS) atau Stasiun Kereta Timur Batavia: sibuk. Stasiun yang dibangun dan dirancang Insinyur Frans Johan Lourens Ghijsels pada awal abad ke-20--tepatnya 1929--itu memang terletak di pusat bisnis Batavia. Kesibukannya bersaing dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Pemerintah kolonial Belanda, yang datang setelah Portugis, dan perkumpulan pedagang Belanda (VOC) merasakan kota itu butuh stasiun kereta api yang besar seperti kota-kota di Eropa. Gaya arsitektur Art Deco yang sedang menjadi tren di Eropa ketika itu--dengan ciri kaca-kaca berbidang luas dan garis-garis simetris tegas--pun menjadi langgam Stasiun Kota.
Kini Beos tetap sibuk plus semrawut. Keluar dari stasiun, kemacetan sudah mencegat. Mikrolet berhenti sembarangan di depan stasiun, ojek sepeda motor dan sepeda mengangkut setumpuk barang, membuat pejalan kaki tak kebagian ruang.
Rasa longgar dan bebas baru dinikmati setelah seratus langkah berjalan ke utara dari perusahaan ekspedisi Tjetot yang terletak di seberang Stasiun Kota. Di sana terhampar lapangan dengan lantai batu: Taman Fatahillah. Ratusan murid sekolah dasar berkerubung memasuki museum di sana, sekelompok turis mancanegara memotret air mancur dengan bangunan kecil di tengahnya. Beberapa remaja putri berseragam sekolah menengah bercengkerama sembari mengisap rokok di bawah pohon. “Uhuk…, uhuk…,” Suara bantuk terdengar dari salah seorang di antara mereka.
Tampak juga pemotret yang sedang mencari sudut cantik untuk pengambilan gambar bagi pasangan yang akan menikah. Bangunan tua di sekitar Taman Fatahillah dan di pinggir Kali Besar memang menjadi latar belakang laris untuk pemotretan seperti itu, atau untuk latar video klip, bahkan pembuatan film.
Sepeda onthel yang biasanya digunakan untuk ojek ikut menjadi latar belakang pemotretat. Untuk menyewa, tarifnya Rp 20 ribu. “Lumayanlah, tak keluar tenaga, duit mengalir,” kata Icang, pengojek sepeda yang mewarisi kendaraan itu dari ayahnya yang juga pengojek. Sehari penghasilannya hanya sekitar Rp 45 ribu. Maklum, tarif ojek onthel lebih murah daripada ojek motor.
Sedikit ke utara lapangan Fatahillah, keadaan mulai tak bersahabat. Tampak seorang berseragam tukang parkir mencoba meminta uang kepada seorang perempuan penjaga meja biliar di salah satu sudut bangunan tua itu. “Minta dua rebu,” katanya. Yang dimintai sewot. “Bisanya minta.” Dalam ruang gedung tua yang gelap memang terdapat beberapa meja biliar. Hanya tiga meja yang digunakan pada siang itu.
Selain tempat biliar “gelap”, di gedung tua sekitar itu juga terdapat toko pakaian “gelap”. Berbagai jenis pakaian tergantung di tembok bangunan tua yang tak terawat. Tapi, bukannya tempat berdagang yang aneh itu tak ada pembelinya. Eddy Koto Rizal, salah seorang pedagang celana jins, mengaku bisa membawa pulang uang hingga Rp 2 juta sehari. “Kalau Lebaran malah bisa Rp 10 juta sehari,” katanya.
Eddy dan pedagang lainnya menyewa bangunan tak bertuan itu dari seorang polisi. ”Daripada dibiarkan kosong, seorang polisi mengorganisasi pedagang kaki lima untuk berdagang di sini,” ujar salah seorang pedagang nyeletuk.
“Aturannya” pun ada. Jika tak mau ditempati orang lain atau tiba-tiba “disewakan” orang lain, lebih baik menyewa penjaga.
Rohadi adalah salah seorang yang mengais rezeki menjaga bangunan tua. Pria 66 tahun asal Tegal itu disewa beberapa pemilik bangunan untuk menunggu gedung tua itu. Untuk menjadi penjaga gedung Tjipta Niaga, dia mendapat Rp 200 ribu per bulan. Kalau ada artis syuting videoklip, dapat tambahan Rp 200 ribu. Kafe Batavia memberinya Rp 1,5 juta, Bank Mega Rp 1 juta per bulan. “Kalau dihitung-hitung, Rp 5 juta bisalah sebulan,” katanya.
Rohadi memang punya kemampuan menjaga gedung, karena dia sudah mengenal setiap sudut Kota Tua. Dia datang ke Jakarta pada 1950, ketika terjadi pemberontakan Darul Islam. “Butuh waktu seminggu untuk sampai ke sini,” kata Rohadi, yang mengaku berjalan kaki menyusuri rel kerata api dari Brebes ke Jakarta, karena rel kereta api saat itu terputus.
Sebelum dipugar pada masa Gubernur Ali Sadikin, menurut Rohadi, Taman Fatahillah merupakan terminal bus, opelet, serta pasar. Kawasan Kota Tua mulai ditinggalkan orang pada pertengahan 1980-an. “Karena kawasan ini tidak aman dan macet,” katanya.
Toh, tetap saja orang yang mencari rezeki tak hengkang dari kawasan Kota Tua.
Bahkan ada saja produk terkenal di sana yang masih selalu dicari orang. Salah satunya adalah di Gang Gloria, yang letaknya tak jauh dari Jalan Pancoran. Jalan sempit itu dipenuhi berbagai jenis makanan khas Cina, mulai dari mi kangkung, siomai, berbagai makanan mengandung babi, hingga yang lebih menantang seperti penyu. Semua ada.
Salah satu yang legendaris adalah gado-gado direksi, yang sudah ada sejak 1967. Meski terletak di gang kecil, penggemar gado-gado direksi bukan sembarang orang. Biasanya bankir atau karyawan kantor sering memesan gado-gado ini untuk makan siang. Omsetnya mencapai Rp 30 juta sebulan. “Bisnis ini saya dapat dari ibu saya. Kebetulan saya satu-satunya anak perempuan dari lima bersaudara,” kata Giok Lie.
Tidak hanya dagangan Giok Lie yang laris manis. Jualan Atim bin Saimin juga tak kalah. Pedagang lektau atau kacang hijau berusia 49 tahun ini baru mulai berjualan sore hari, sekitar pukul 16.30. Tempatnya di depan Apotik Bintang Semesta, Pancoran. Tapi, menjelang magrib, lektau yang dijual Rp 3.000 semangkok sudah ludes. “Setiap hari, saya dapat penghasilan bersih Rp 150 ribu. Lumayan buat membiayai lima anak saya,” kata warga Angke yang sudah berjualan lektau selama 33 tahun ini.
Tatkala gelap dan lampu-lampu mulai menyala, pencari rezeki pun berganti wajah. Di kawasan pecinan Kota Tua, karaoke, klub malam, dan panti pijat mulai buka. Di ujung jalan, dekat Jembatan Kota Intan--yang kini cuma hiasan dan kenangan--tampak sekelompok pekerja seks menjajakan diri. Pelanggannya sopir, kuli, dan lelaki iseng lainnya. Sampai saat azan subuh mengalun dari masjid kecil tak jauh dari jembatan itu, orang-orang yang mengais rezeki di Kota Tua tetap saja ada.
Ahmad Taufik, Amandra Mustika Megarani
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















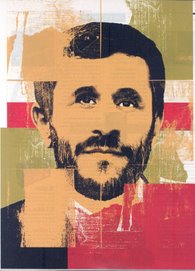









Tidak ada komentar:
Posting Komentar