Sampai sekarang ini Qom masih memiliki daya tarik bagi santri asal Indonesia.
Indonesia salah satu pemasok santri bagi hauzah atau madrasah di Qom, Iran. Sejak kemenangan revolusi Islam Iran pimpinan Imam Khomeini, negeri para mullah itu menjadi daya tarik bagi pemuda Indonesia untuk belajar agama. Sebelumnya, minat pelajar Indonesia menimba ilmu agama umumnya ke Universitas Al-Azhar Mesir, Ummul Qurra Arab Saudi, Irak, dan Pakistan.
Saat ini, menurut catatan Yayasan Jahani, lembaga yang bergerak mencari dan memantau lulusan hauzah Qom di mancanegara, tercatat 150 alumnus hauzah Qom di Indonesia. “Saya berharap mereka bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Percuma saja sudah jauh-jauh ke Iran dan diberi fasilitas tapi tak menjadi manfaat bagi umat,” kata pemimpin Jahani, Ayatullah Murtadha Muqtadai, yang berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Lulusan Qom di Indonesia kini tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Ada yang menjadi pendakwah, guru, penulis, bahkan politikus. Saat ini masih ada ratusan santri Indonesia yang belajar di Qom. Di bawah ini beberapa profil alumnus hauzah Qom.
Musa Kadzim Siraj, 43 tahun,
Pria kelahiran Bangkalan, Madura, 1963 ini semula mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, selama dua tahun. Tak puas dengan pendidikan yang diterimanya, Musa mulai berkorespondensi dengan lembaga pendidikan yang ada di Timur Tengah: Arab Saudi, Mesir, dan Iran.
Ternyata proposalnya diterima di Iran. “Saya berminat ke Iran karena negeri itu punya daya tarik yang luar biasa. Bahasa dan budaya Persia tua. Iran salah satu kekuatan timur pada zaman rasul. Dan tentu saja revolusi Islam Iran yang dibawa Imam Khomeini,” katanya.
Namun tak mudah untuk bisa masuk ke negeri itu. Apalagi pemerintah Orde Baru saat itu sedang ketakutan dengan isu ekspor revolusi Islam yang diembuskan negara Barat yang anti terhadap pemerintahan Khomeini. Walau tanpa visa, Musa langsung terbang ke Karachi, Pakistan, pada 1985. Ia sempat terdampar selama tiga bulan dan ditampung oleh mahasiswa asal Iran, Mr Daud, di Dow Medical Centre, sebuah asrama mahasiswa Iran yang dibangun Shah untuk mahasiswa Iran di Pakistan.
Setelah memegang visa Iran, Musa lebih dulu belajar bahasa Persia di Nejafabad, delapan kilometer dari Kota Isfahan, selama setahun. Setelah itu, bersama 10 orang lainnya dia “dijebloskan” ke Hauzah Ilmiyah Hujatiyah, Qom. Kampusnya hanya 100 meter dari makam Hazrat Maksumah Fatimah. Sebelumnya, sudah ada enam orang Indonesia lain belajar di madrasah yang memang khusus untuk orang asing itu.
Di sekolah itu Musa, dengan bahasa pengantar Arab, belajar mengkaji akidah Islam, bahasa Arab, fikih, tafsir, dan logika (mantiq). Musa belajar Babul Hadi Asyar (akidah karya Alamah al-Hlli) dari Hujatul Islam Jafar Hadi, murid kesayangan Ayatullah Jafar Subhani. Ia juga belajar Mantiq al-Mudaffar 2 jilid karya Dr Syekh Nabil, Fiqh, Tahrir Wasilah karya Imam Khomeini, dan Tafsir Al Mizan fi Tafsirul Qur’an karya Ayatullah Muhammad Thabathabai. “Yang paling berkesan belajar di Iran adalah perilaku ulama-ulama yang ada di Qom, yang begitu baik menghargai pelajar-pelajar dari Indonesia, tidak merasa lebih tinggi atau pintar. Mereka benar-benar memahami Islam dengan baik dari perilakunya,” ujar Musa.
Setelah lima tahun di Qom, 1990, Musa kembali ke Indonesia, langsung bersilaturahmi ke ulama-ulama, terutama di Martapura, Kota Baru, dan Banjarmasin, Kalimantan. “Di Martapura ada Guru Zain. Martapura itu seperti Qom. Seluruh ulama Kalimantan untuk mengkaji irfan harus ke Guru Zain itu,” katanya.
Selain mengajar bahasa Persia di Pusat Kebudayaan Islam (ICC), Jakarta, Musa aktif berdakwah di kalangan bawah, waria, dan buruh migran. Bulan lalu, selama sebulan Musa mengadvokasi buruh migran di Hong Kong. “Pemerintah harus memperhatikan buruh migran yang menghasilkan devisa tidak kecil bagi negeri ini,” ujarnya.
Abdullah Beik, 37 tahun
Berawal dari membaca buku-buku anti-Syiah dan Imam Khomeini, pelajar Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPIA) milik pemerintah Arab Saudi itu kemudian justru penasaran terhadap ajaran ahlul bait. “Apalagi setelah menonton film detik-detik kematian Imam Khomeini,” ujar Abdullah Beik. Dengan modal bahasa Arab dari LPIA yang bagus, lulusan SMA di Sumenep, Madura, ini melamar ke lembaga pendidikan di Iran,
Pria kelahiran 1970 tersebut masuk ke Hauzah Hujatiyah Qom pada 1991. Lulus sarjana jurusan syariah, ia lalu pulang ke Indonesia. “Pendidikan di sana sudah modern. Saya sempat belajar langsung dari murid Imam Khomeini, Syekh Nur Muhammadi,” kata Beik.
Saat masih mahasiswa, Beik tinggal di asrama dengan para pelajar bujangan lainnya.Tak puas hanya jadi sarjana, setelah menikah, Beik memboyong istrinya mengambil gelar master teologi dan filsafat di Sekolah Tinggi Imam Khomeini, Qom, sejak 1999. “Saya tinggal di rumah yang disediakan pemerintah Iran khusus untuk mahasiswa asing yang sudah berkeluarga,” ujarnya.
Ayah satu anak ini kembali ke Indonesia pada 2004 dan kini menjadi Manajer Pendidikan dan Dakwah ICC, Jakarta. Sebagai lulusan Qom, Beik juga memantau rekan-rekannya yang aktif di berbagai bidang. “Setiap tahun kami bertemu dalam silaturahmi nasional,” ujarnya.
Dibandingkan dengan India, Pakistan, Turki, atau Afganistan, menurut Beik, lulusan Indonesia tak terlalu banyak. “Jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, atau Filipina, Indonesia memang lebih banyak,” kata penggemar film Oshin itu.
Ali Hussein, 32 tahun
Tiga tahun nyantri di Pesantren Al-Hadi, Pekalongan, Jawa Tengah, pimpinan Habib Ahmad Baragbah, ia tak cukup puas. Melalui relasi yang dimiliki ajengan pesantren itu, Ali Hussein, yang sering dipanggil sebagai Ali Pati, berangkat ke Qom pada 1994.
Sebelum diterima di Hauzah Hujatiyah, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, itu belajar bahasa Persia selama enam bulan di Madrasah Sahabiyah. Di Hujatiyah, Ali bersama pelajar mancanegara asal Tunisia, Sierra Leone, Afrika Selatan, Pakistan, India, dan Malaysia belajar ilmu-ilmu teologi, akidah, fikih, bahasa Arab, ushul fiqh, dan tafsir Al-Quran. “Kelas berisi hampir 40 orang, tiap pagi belajar tiga jam dan sore tiga jam,” katanya.
Selain ustad-ustad yang disediakan madrasah, sering datang juga dosen tamu. “Kami pernah diajar oleh pemimpin Hizbullah Libanon, Hassan Nasrallah,” kenang Ali. Sekretaris Direktur ICC ini punya alasan memilih belajar di Qom. Kota itu dianggap sebagai pusat perkembangan ilmu makrifah Islam, terutama bidang-bidang filsafat, dan ilmu kalam. “Banyak sekali ulama lulusan Qom, bahkan sebagian besar ulama ahlul bait di dunia ini pernah belajar di Qom, marja’-marja’ terkenal juga punya kedudukan di Qom,” katanya. Lulus setingkat sarjana, Ali sempat bekerja selama dua tahun untuk Radio Republik Islam Iran (IRIB) seksi Melayu.
Ammar Fauzi, 33 Tahun
Berawal dari suka filsafat, santri YAPI, Bangil, Jawa Timur, ini mengakses karya-karya orang Iran. Lalu Ammar berhubungan dengan guru-guru yang datang dari Qom.
Pria kelahiran Purwakarta, Jawa Barat, itu nekat pergi dengan tiket satu kali jalan (one way). “Entah bagaimana situasi masa itu, rombongan kecil kami harus mengambil visa entry dari Kedutaan Iran di Kuala Lumpur,” katanya. Lebih dari seminggu Ammar dan kawan-kawan harus berada di Singapura dan Malaysia. Setelah visa diperoleh, barulah bisa berangkat ke Teheran. “Proses perjalanan seperti ini tidak dialami lagi oleh mereka yang datang setelah saya,” ujarnya.
Di Qom, seperti santri Indonesia lainnya, ia diceburkan ke Hauzah Hujatiyah (1994-1998), lalu dilanjutkan ke Hauzah Muassasah Pezwuhesh, Institut Penelitian Misbah Yazdi (1995-2001). Kini Ammar adalah mahasiswa semester akhir program doktoral filsafat Islam Hauzah Imam Khomeini--sejak 2000. Di tempat kuliah, Ammar mendapat pelajaran bahasa Persia, sastra Arab, ilmu-ilmu agama, logika Aristotelian, teologi, filsafat, fisiologi, psikologi, dan matematika. “Sekarang banyak bermunculan guru pemikir muda yang melakukan perimbangan dan terobosan baru di banyak bidang ilmu,” ujarnya.
Ketika awal masuk Qom, Ammar tinggal di asrama. “Seperti tinggal di rumah sendiri,” katanya. Keragaman pelajar waktu itu cukup terlihat. Kini keragaman itu jauh lebih kompleks dan fasilitasnya jauh lebih memadai. Ammar, yang sudah berkeluarga, tak lagi tinggal di asrama. “Kami tinggal di perumahan dan apartemen yang telah disediakan,” ujarnya. Ammar tinggal lima kilometer dari tempat kuliahnya di kawasan Haram Sayidah Ma'sumah.
Tiap bulan Ammar mendapat biaya hidup dari marja’-nya berkisar 250 ribu tuman atau senilai Rp 2,5 juta. “Cukuplah untuk hidup di sini,” katanya. Bagi Ammar, jalan-jalan di pertokoan buku sudah merupakan hiburan.
Abdurahman Baragbah, 46 tahun
Abdurahman Baragbah sudah lelah tinggal di Iran. “Saya mau kembali ke Indonesia, saya sudah bikin surat pengunduran diri,” ujar penyiar Radio Republik Islam Iran seksi Melayu itu. Pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang menguasai bahasa Arab, Persia, dan Inggris ini sudah lebih dari 20 tahun berada di Iran.
Tiga belas tahun ia menjadi penyiar dan penerjemah di IRIB Teheran, setelah delapan tahun mondok di Hauzah Hujatiyah Qom. ”Dulu, ketika awal belajar di Qom, kayak di pesantren, kami harus menempel seorang ulama,” katanya. Namun belakangan sistem itu diubah menjadi sistem modern dengan kelas dan hitungan SKS.
Ada kenangan yang tak terlupakan saat ia berada di Qom. Ketika rudal-rudal Irak menghantam sasaran sipil, para ulama meminta para pelajar mancanegara pindah untuk sementara. “Kami semula tidak ada yang mau, dan dengan bersemangat ingin bertahan bersama-sama di pesantren kami. Namun marja’ dengan tegas mengatakan, ini perintah, kami tak bisa menolak,” kata ayah dua anak ini.
Ustad Aman, begitu teman-teman memanggilnya, diberi tanggung jawab mengurusi kepindahan para pelajar ke Mashad. Dengan fasilitas yang terbatas dan waktu menunggu beberapa hari, pemerintah Iran menyediakan dua bus kota--karena bus antarkota dipakai untuk membawa para pejuang ke front depan. Selama 20 jam bus menembus jalan yang dingin dan bersalju.
Dua bulan di Mashad, akhirnya para pelajar kembali menuntut ilmu di Qom. Aman segera kembali ke Indonesia jika proses pengunduran dirinya diterima. Dua anaknya sudah lebih dulu dikirim bersekolah di Yayasan Pesantren Islam di Bangil, Jawa Timur. “Saya ingin mendirikan sekolah Islam modern di Purwokerto,” katanya bercita-cita. (A.T)
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















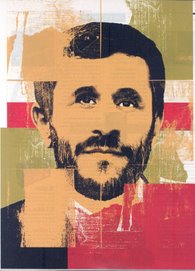









Tidak ada komentar:
Posting Komentar