Perempuan sering kali ditempatkan, sebagai warga negara kelas dua dalam sebuah masyarakat, sesudah pasangan mereka, pria. Tetapi, perempuan selalu menjadi korban pertama dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam bidang politik, perempuan tak mendapat tempat yang pantas di pentas politik. Perempuan berulangkali hanya diikutsertakan, bukan menjadi penentu keputusan dalam pengambilan kebijakan. Tak heran jika keputusan politik selalu merugikan kaum perempuan dalam berbagai hal.
Namun, saat terjadi situasi chaos dan ketidakstabilan politik, perempuan lah yang pertama kali menjadi korban. Dalam peristiwa kekerasan politik tahun 1965 di Indonesia, ribuan perempuan mati dan menjadi tahanan politik. Dalam kekerasan politik di Aceh, perempuan menjadi korban langsung dan tak langsung. Menjadi korban langsung, selain mati terbunuh saat tak bersenjata, perempuan diperkosa dan dilecehkan hak dan kehormatannya. Secara tak langsung perempuan menjadi korban saat suaminya mati dibunuh tentara alias menjadi janda.
Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia Timur, Tenggara, Australia maupun kawasan Pasifik. Penahanan yang berkepanjangan terhadap Aung San Syu kyi di Burma hingga kini, contohnya menunjukkan perempuan yang mencoba bangkit melawan dilemahkan oleh kekuatan militer.
Di Philipina, janda diktator Ferdinand Marcos, Imelda, penah dipakai untuk melawan Corry Aquino yang didukung rakyat. Corry adalah janda Ninoy Aquino yang dibunuh Marcos saat baru tiba di bandar udara Philipina, setelah dari pengasingannya di Amerika Serikat. Diktator Marcos, takut terhadap lawan-lawan politiknya, jalan satu-satunya adalah membunuhi mereka. Corry lah yang menuntut balas, dan memberikan kekuasaan kepada demokrasi rakyat di Philipina. Kekuasaan sekarang yang dipegang oleh Arroyo Macagapal, hanyalah meneruskan jalan setapak yang sudah dirintis oleh Corry aquino. Namun, tak sedikit halangan yang terjadi terhadap Arroyo kini, terutama gangguan dari suaminya, yang “merasa” turut berkuasa.
Di Indonesia, pengalaman yang sama pernah terjadi saat Megawati Sukarnoputri menjadi presiden. Hampir tidak ada kebijakan publik yang dibuat oleh Presiden Megawati, memberi nilai ‘plus” bagi kaum perempuan.
Hambatan terhadap perempuan sering kali juga datang dari penguasa tafsir agama. Agama, selain alasan politis juga sering dipakai sebagai alasan untuk menghambat perempuan-perempuan yang ingin maju. Padahal, inti dari ajaran semua agama tak membeda-bedakan jenis kelamin. Karena ajaran agama itu untuk semua manusia. Cuma terjadi perbedaan penafsiran, yang didominasi kaum laki-laki sehingga peran perempuan disisihkan dalam beberapa segi kehidupan.
Di kawasan Asia Timur, Tenggara, Australia dan kepulauan Pasifik, terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan. Yang tercatat banyak pemeluk agama Islam –nya hanya terdapat di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Ajaran Islam yang dominan dalam masyarakat itu mempengaruhi setiap penentu dalam mengambil kebijakan. Di Philipina, walaupun negaranya didominasi pemeluk Katolik, tetapi di beberapa negara bagian, seperti di Pulau Mindanau dan sekitar, pemeluk Islam mendominasi wilayah itu. Sehingga kebijakan juga harus diambil sesuai komunitas di masyarakat itu.
Kedudukan perempuan dalam kebudayaan Indonesia mempunyai banyak segi. Tak bisa diidentikkan dengan satu tipe. Ini terjadi karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Dalam suku Minangkabau, di Sumatera Barat, misalnya perempuan mempunyai peran yang dominan dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan lebih berhak mendapat hak warisan dibandingkan laki-laki. Dalam hal perkawinan, perempuan suku Minangkabau juga bisa ‘membeli’ laki-laki yang diinginkannya. Seorang laki-laki yang berpendidikan tinggi akan ‘dibeli’ mahal oleh perempuan Minangkabau.
Sistem matrilinear (motherhood) dalam suku Minang memang mengejutkan. Karena justru suku di Sumatera bagian Barat itu terkenal dengan keteguhan memegang ajaran agama Islam. Bahkan dalam konsepnya terkenal motto “Adat bersanding Syara. Syara bersandung Kitabullah’’ Artinya ada harus sesuai dengan syariat agama dan syariat agama (Islam) harus sesuai dengan Kitab Suci Al-Qur’an.
Padahal ajaran Islam, dari tempat agama itu berasal di tanah Arab, terkenal dengan ajaran yang sangat kelaki-lakian. Zaman pada saat Nabi Muhammad lahir di tanah Arab, bagi suku/qabilah yang hidup di tempat itu adanya anak perempuan dianggap musibah, karena itu apabila ada anak perempuan yang lahir segera dibunuh. Karena dianggap akan menyusahkan keluarga itu.
Memelihara anak-anak laki-laki dalam masa itu di tanah Arab dianggap merupakan investasi masa depan. Karena laki-laki bisa segera bekerja menghasilkan nafkah membantu keluarga. Berbeda blan memiliki anak perempuan, hanya bisa dipelihara sampai tiba waktunya diambil oleh (dikawin). Belum lagi resiko yang akan ditanggung bila anak perempuan itu tak ada yang mau mengawini karena cacat atau kekurangan lainnya, dan mengalami perkosaan.
Tapi , hanya jarak sepelemparan batu masih di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, lebih khusus lagi suku batak, yang kebanyakan beragama kristen, justru sangat kuat garis kebapakan (manhood). Hanya anak laki-laki yang diakui dan berhak memakai nama bapak atau garis keturunannya (marga).
Di tempat lain, masih di Indonesia, walaupun dalam peri kehidupannya menganut garis kebapakan, tetapi perempuan lebih dominan sebagai tulang punggung pencari nafkah keluarga. Misalnya, suku di Pulau Bali, perempuannya pergi mencari kerja, sedangkan laki-laki peketrjaannya hanya bermain judi sabung ayam atau berleha-leha di rumah menjaga anak. Indonesia memang sebuah negara yang unik, yang terdiri dari banyak suku, agama dan keprercayaan.
Namun, arus besar dalam masyarakat Indonesia, menunjukkan perempuan menjadi orang pinggiran, warga negara kelas dua, dibandingkan laki-laki. Baik karena dominannya agama Islam, juga karena dominannya suku yang menganut garis keturunan kebapakan. Tak heran kebanyakan pahlawan nasional adalah laki-laki, justru pahlawan dari Aceh yang menjadi pahlawan nasional kebanyakan perempuan.
Memang sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, para perempuan Aceh melawan secara fisik usaha-usaha penjajahan, seperti yang datang dari Inggris, Portugis dan Belanda. Itu karena para lelaki, telah kalah dan menyerah ke tangan para penjajan, mereka meneruskan perjuangan itu, melawan secara gerilya di hutan atau tangkas di laut seperti Keumalahayati di abad 17 yang menjadi pemimpin wanita di laut melawan pelaut Portugis yang akan menyerang Aceh.
Namun, setelah Indonesia merdeka, perempuan semakin tersisihkan perannya dalam panggung politik, maupun sebagai penentu kebijakan bangsa. Sehingga setiap putusan politik yang diambil, selalu bias gender dan mempersempit ruang gerak perempuan. Selama Presiden Soeharto berkuasa (1965-1998-sering disebut sebagai orde baru untuk membedakan orde lama pimpinan Presiden Soekarno) perberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan.
Setelah Soeharto tak lagi berkuasa, meminggirkan kaum perempuan masih terus terjadi. Lewat “demokrasi” kelompok-kelompok keagamaan atau organisasi massa tertentu menekan penguasa-penguasa daerah atau partai politik untuk terus meminggirkan kaum perempuan. Mulai dari alasan peraturan daerah anti maksiat, peraturan daerah berdasarkan syariat Islam, sampai rancangan Undang-undang Anti pornografi dan Porno Aksi yang isinya, tidak mendudukkan perempuan dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Alih-alih alasan mau menjaga martabat perempuan, para pendukung peraturan bernuasansa syariat Islam, lebih berusaha memaksakan kehendaknya. Pengalaman di Afghanistan saat kaum Taliban berkuasa, perempuan menjadi kaum tertindas. Perempuan tak boleh sekolah, bekerja, tapi para Taliban tak pernah mencegah perempuan untuk menjadi peminta-minta. Dalam sejarah pemerintahan para Kalifah Islam, para penguasa yang menggunakan khilafah Islamiyah, justru, “memenjarakan” perempuan dalam ruang-ruang harem. Tak jarang para Raja Islam yang berkuasa menggunakan kitab suci dan para ulama melangengkan peminggiran kaum perempuan, dengan menjadikannya budak nafsu, gundik ataupun selir.
Para penguasa itu, dengan para ulamanya yang 100 persen laki-laki (kalau perempuan hanya sebatas sampai ustadzah/guru agama) menggunakan agama Islam, sesuai penafsirannya sendiri. Padahal ajaran Islam dibangun berdasarkan persamaan baik dari gender (jenis kelamin) maupun status sosial. Karena dalam Al-Quran, jelas disebutkan orang yang tinggi derajatnya, adalah orang yan berilmu dan bertakwa. Tak disebut soal jenis kelamin ataupun kedudukan sosial.
Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Islam tak membeda-bedakan jenis kelamin. Tuhan dengan caranya sendiri, tak memberikan keturunan (anak) laki-laki kepada nabi Muhammad, dalam lingkungan Kabilah (suku) Arab yang sangat mengagungkan kedudukan laki-laki. Kini tak perlu lagi menggunakan “tangan” Tuhan untuk bisa mendudukan perempuan setara dengan laki-laki. Karena toh, manusia sudah memiliki akal. Hanya kaum tak berakalah yang masih membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin dan status sosial.(sekian)
Tiket Bis
10 tahun yang lalu




















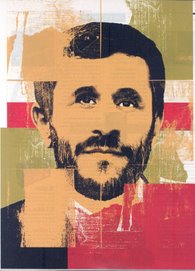









Tidak ada komentar:
Posting Komentar